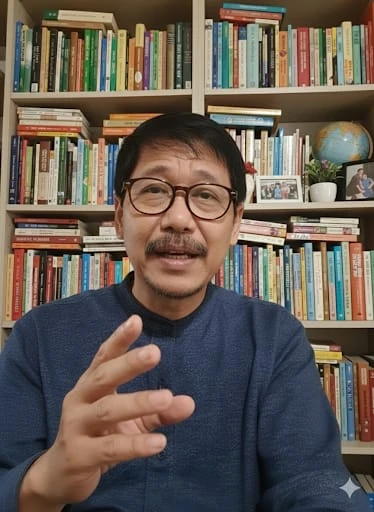Oleh: Muliadi Saleh*
Kekuasaan, dalam sejarah manusia, selalu memiliki aroma. Kadang wangi legitimasi, kadang bau anyir kepentingan, kadang harum pengabdian, kadang pula busuk oleh kelalaian.
Tetapi ada satu aroma yang kini makin sulit disembunyikan—aroma ekologis dari keputusan-keputusan politik yang merusak keseimbangan alam. Inilah yang saya sebut sebagai ekologi kekuasaan: hubungan antara tata kelola, kepentingan, dan dampaknya pada bumi yang menjadi rumah bersama.
Kekuasaan tidak pernah bekerja di ruang kosong. Ia bekerja di tanah yang bisa longsor, di hutan yang bisa habis, di sungai yang bisa meluap, dan di udara yang bisa sesak.
Setiap kebijakan adalah benih: ada benih yang tumbuh menjadi pohon kehidupan, ada pula yang tumbuh menjadi semak belukar konflik ekologis. Celakanya, terkadang akar masalah bencana ekologis justru tumbuh dari meja rapat, bukan dari perut bumi.
Ekologi kekuasaan memperlihatkan kepada kita bahwa setiap keputusan—izin membabat hutan, proyek besar yang meratakan bukit, pembangunan yang mengabaikan daerah resapan—adalah garis takdir yang akan kembali ke pangkuan masyarakat.
Kekuasaan yang tidak memahami ekologi ibarat arsitek yang membangun rumah tanpa membaca kontur tanah: kelak bangunan itu akan roboh, dan ia akan menyalahkan hujan, bukan dirinya sendiri.
Dalam banyak bencana di Sumatera dan daerah lain, kita menemukan pola berulang yang sulit dibantah. Hutan ditebang bukan karena masyarakat desa ingin kaya, tetapi karena kekuasaan memberi jalan bagi modal untuk masuk lebih dalam.
Sungai kehilangan lebar alaminya bukan karena penduduk ingin bermewah-mewah, tetapi karena kebijakan ruang sering kali dikendalikan oleh kepentingan jangka pendek. Konflik satwa dengan manusia meningkat bukan karena satwa agresif, tetapi karena ruang jelajah mereka dicincang oleh peta-peta yang dipelototi dari balik meja kantor.
Ekologi kekuasaan adalah cermin yang tidak pandai berdusta. Ia memperlihatkan bagaimana aliansi antara kekuasaan dan modal membuat alam menjadi objek yang dapat dinegosiasikan nilainya. Jalan setapak kuno yang dulu dilalui gajah dibelah menjadi jalan tambang.
Sungai yang mengalir lembut dalam himpitan demi estetika kota. Lahan gambut yang menyimpan riwayat ribuan tahun dipaksa menjadi arena ekonomi sesaat. Kekuasaan bekerja, tetapi tanpa ekologi, ia bekerja seperti mata yang menatap jauh sambil mengabaikan jurang di depan kaki.
Namun, seperti alam, kekuasaan juga memiliki titik balik. Ketika bencana datang, ia tidak memilih korban. Air bah tidak membedakan pendukung atau oposisi. Longsor tidak peduli warna bendera.
Di situlah paradoks kekuasaan membentang: keputusan yang diambil oleh segelintir orang menghasilkan penderitaan bagi banyak orang—termasuk mereka yang bersandar pada kekuasaan itu sendiri.
Ekologi kekuasaan mengajarkan kita bahwa alam adalah pemimpin yang paling sabar tetapi sekaligus paling tegas. Ia memberi peringatan berulang, sering kali dalam bentuk kecil: banjir setinggi mata kaki, retakan kecil di tepi bukit, mata air yang mengering. Ketika peringatan itu diabaikan, ia mengirimkan teguran yang lebih keras. Alam tidak membalas dendam; ia sekadar menegakkan hukumnya.
Kekuasaan yang berkelanjutan—sustainable power—harus mulai membaca bahasa alam sebagai 'dokumen politik'. Harus memahami bahwa hutan bukan sekadar aset, tetapi stabilisator kekuasaan itu sendiri.
Sungai bukan sekadar sumber air, tetapi penyangga kehidupan sosial. Rawa bukan ruang kosong, tetapi penampung memori ekologis. Menjaga alam adalah salah satu bentuk pemerintahan yang paling bijaksana, meski tidak selalu paling populer.
Generasi mendatang akan menilai para penguasa bukan dari jumlah proyek yang diresmikan, tetapi dari seberapa dalam hutan tetap tegak, seberapa panjang sungai tetap mengalir, dan seberapa aman masyarakat tinggal di rumah-rumah mereka.
Ekologi kekuasaan adalah pengingat bahwa pembangunan tanpa keseimbangan hanya menciptakan generasi yang hidup dalam ketakutan: takut banjir mendadak, takut longsor, takut kehilangan kampung halamannya.
Kekuasaan yang benar adalah yang mampu memandang manusia dan alam sebagai satu kesatuan ruang. Bahwa tata kelola bukan hanya tentang administrasi, tetapi tentang menjaga harmoni.
Bahwa keputusan besar tidak boleh mengabaikan suara akar, suara tanah, suara air, suara angin yang mengingatkan bahwa kehidupan tidak diciptakan untuk dieksploitasi, melainkan untuk dirawat.
Barangkali inilah saatnya kekuasaan meneladani cara alam memimpin: tidak sombong, tidak tergesa, tetapi tegas dan penuh hikmah. Alam selalu memberi ruang bagi yang kecil, memberi perlindungan bagi yang lemah, dan menghukum yang melampaui batas.
Seandainya kekuasaan mau meniru sedikit saja cara alam bekerja, niscaya hubungan antara pembangunan dan kelestarian tidak lagi menjadi konflik, melainkan menjadi simfoni.
Sebab pada akhirnya, kekuasaan yang menaklukkan alam hanya memenangkan waktu yang singkat. Tetapi kekuasaan yang merawat alam akan memenangkan masa depan yang panjang.
Dan di sanalah peradaban menemukan bentuk terbaiknya: ketika yang memimpin belajar dari bumi, dan yang dipimpin hidup dalam damai bersama ruang yang menopangnya.
*Penulis adalah Esais Reflektif & Arsitek Ekologi Sosial