.webp)
Mereka tahu, sesuatu yang bisa dinikmati tidak selalu boleh dikonsumsi. Seks, bagi mereka, adalah persemaian. Dan seperti petani yang baik, mereka tahu kapan waktu yang tepat untuk menanam.
Eyo malape Jumaa teisinini... (Hari baik adalah Jumat dan Senin..)
Bahkan waktu berhubungan pun dipilih dengan sadar. Bukan karena takhayul, tapi karena keyakinan bahwa segala hal ada ukurannya. Dan anak yang lahir bukan sekadar produk, melainkan warisan.
Maka jangan heran jika masyarakat Buton membicarakan seks dengan penuh kehati-hatian. Mereka tidak menyebutnya “bercinta” atau “berhubungan”. Mereka menyebutnya “menanam”. Dan rumah tangga adalah kebun.
Ositumo wine inda momabongko / Tokaindeana naile muri-murina (Bibit tak pernah rusak, untuk persemaian hari esok.)
Saya terdiam lama di bait ini. Sebab tak banyak budaya yang dengan tenang, tapi jelas, menempatkan hubungan suami-istri sebagai sesuatu yang harus dijaga dengan cinta dan iman.
Di sini, seks bukan produk instan. Ia adalah upaya menciptakan manusia baru, yang kelak menanggung sejarah. Maka ia harus dilakukan dengan hormat, bukan buru-buru. Dengan kasih, bukan paksaan. Dengan iman, bukan hanya ingin.
Kabanti juga tak segan menyebut kejahatan. Zina digambarkan dengan keras: bukan karena benci pada pelaku, tapi karena cinta pada tatanan. Jika rumah tangga adalah kebun, maka masuk ke kebun orang adalah perusakan. Dan pelakunya bukan manusia, tapi “hewan yang memakan tanaman orang”.
Kaapaakao ‘adatina kadadi / Beapesua inuncana koinawuna... (Adat kebiasaan hewan, ingin masuk ke kebun orang...)
Bahasanya memang tegas. Tapi dalam budaya Buton, kehormatan bukan mainan. Tubuh bukan barang murah. Seks bukan hanya soal suka sama suka. Ia menyangkut nama baik, marwah, dan keberlangsungan generasi.
Karena itu, siapa pun yang menghancurkan kebun orang, akan ditolak oleh masyarakat. Ia dilempar. Ditombak. Bahkan “ditembak sampai jatuh”.
Kita mungkin menganggap ini terlalu keras. Tapi kadang, kebudayaan memang menyimpan kekuatan dalam perumpamaan. Ia bukan ingin menyakiti, tapi memberi batas. Dan batas itu penting agar manusia tidak lupa menjadi manusia.
Di akhir kabanti, kita diajak membayangkan hasil dari hubungan yang diberkahi. Anak-anak yang tumbuh bukan seperti benalu, tapi seperti kelapa: muda segar, tua harum.
Kalimbunguna anamisimo isyqi... (Kelapa mudanya memberi rasa asyik, kelapa tuanya harum nikmat...)
Saya membayangkan, bagaimana jika bait-bait seperti ini dibacakan di sekolah. Bukan sebagai pelajaran agama, tapi sebagai bagian dari hidup. Kita tak kekurangan edukasi seks. Yang kita kurang adalah edukasi makna.
Tentang mengapa tubuh harus dihormati. Tentang bagaimana cinta tak boleh lepas dari tanggung jawab. Tentang mengapa anak-anak pantas dilahirkan dari cinta yang sah dan sadar.
Kabanti Kaluku Panda mungkin tidak populer di TikTok. Tapi ia membawa suara yang pelan dan mendalam—suara yang kita butuhkan di dunia yang terlalu bising ini.
Suara tentang kesucian yang bukan tabu, tapi rahmat. Tentang tubuh yang bukan aib, tapi amanah. Dan tentang seks yang bukan permainan, tapi benih masa depan.
Dalam falsafah Buton, ada satu istilah yang mendalam: kangkilo—proses penyucian diri, pembersihan jiwa dari hal-hal kotor yang melekat pada batin. Kangkilo bukan sekadar ritual; ia adalah kesadaran bahwa manusia tak luput dari kegelapan, dan perlu ruang untuk menjernihkan kembali hidupnya.
Mungkin, seks—jika disalahgunakan, jika dijalani tanpa nilai dan hanya jadi alat dominasi—juga butuh di-kangkilo-kan. Dibersihkan dari nafsu yang membutakan, dari relasi yang timpang, dari tradisi yang membungkam.
Dan siapa tahu, membaca ulang kabanti ini dengan hati yang jernih, adalah bentuk kangkilo tersendiri bagi kita hari ini. Sebuah upaya bukan untuk menolak warisan, tapi untuk membersihkannya, menyiraminya kembali dengan cahaya kesadaran, serta menjadikannya bermakna.
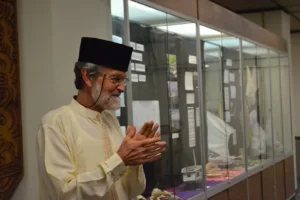

-300x169.webp)








