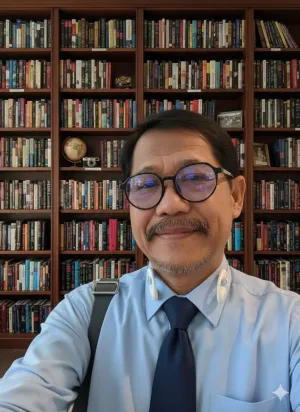UNHAS.TV - Pada era digital dan mobilitas tinggi, di balik unggahan senyum dan pencapaian di media sosial, diam-diam ada luka batin yang menganga dihadapi kalangan generasi muda.
Gangguan mental health atau kesehatan mental kini bukan lagi isu pinggiran. Ia telah menjelma menjadi salah satu tantangan serius kesehatan masyarakat di Indonesia, terutama bagi kelompok usia 10 hingga 17 tahun.
Data Survei Kesehatan Mental Remaja Nasional menunjukkan kenyataan mencemaskan: sekitar 34,9% atau setara 15,5 juta remaja mengalami satu atau lebih masalah kesehatan mental.
Dari jumlah itu, 5,5% terdiagnosis gangguan mental dan hanya 2,6% yang mengakses layanan profesional. Sebuah ketimpangan besar antara kebutuhan dan ketersediaan layanan.
Dosen dan praktisi psikologi sosial dan kesehatan mental Universitas Hasanuddin (Unhas), Syurawasti Muhyidin SPsi MA menjelaskan bahwa faktor utama penyebab gangguan ini sangat kompleks dan melibatkan banyak lapisan kehidupan sosial.
“Yang pertama tentu saja faktor lingkungan. Mulai dari lingkungan terdekat seperti keluarga, komunitas, hingga budaya. Beberapa tradisi atau kebiasaan tertentu bisa menekan remaja dengan ekspektasi dan kewajiban yang terlalu berat,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa gangguan mental tidak semata muncul dari dalam diri individu. Ketahanan mental remaja terbentuk dari interaksi antara individu dengan lingkungan sosialnya.
Ketika tekanan sosial tidak diimbangi dengan dukungan emosional yang sehat, risiko gangguan mental meningkat tajam.
Jenis gangguan yang umum ditemukan di kalangan anak muda antara lain gangguan emosional, depresi, dan kecemasan.
Gangguan ini, menurut Syurawasti, tak bisa dilepaskan dari peran media sosial. Fenomena perbandingan sosial menjadi pemicu signifikan.
“Kita cenderung membandingkan pencapaian kita dengan apa yang orang lain tampilkan di media sosial. Itu bisa memunculkan perasaan rendah diri, tidak cukup berhasil, atau tidak berharga,” paparnya.
Studi dari Journal of Adolescence (2023) mendukung temuan ini. Penelitian tersebut menunjukkan korelasi antara penggunaan media sosial secara intensif dengan peningkatan gejala kecemasan dan depresi, khususnya pada remaja perempuan.
Paparan terhadap standar hidup yang tak realistis dan ekspektasi sosial digital memperparah ketidakpuasan diri dan mempercepat penurunan kesehatan mental.
Syurawasti menambahkan bahwa pendekatan preventif jauh lebih penting daripada sekadar penanganan pasca-terdiagnosis. Ia menyebut dua hal utama yang harus diperkuat: kontrol diri dan resiliensi, serta sistem dukungan dari lingkungan terdekat.
“Remaja butuh pendampingan dari keluarga. Keluarga yang sehat bisa menjadi tempat aman bagi mereka untuk bercerita dan meminta bantuan. Relasi yang suportif sangat krusial untuk membentuk daya tahan mental,” jelasnya.
Ia menggarisbawahi bahwa peran keluarga tak bisa digantikan. Dalam konteks remaja yang masih mencari jati diri dan rentan terhadap tekanan, keberadaan orang tua dan lingkungan yang peduli menjadi penentu utama arah perkembangan psikologis mereka.
Pemerintah pun dinilai perlu membangun pendekatan yang lebih integratif. Tak hanya penanganan medis, tetapi juga edukasi kesehatan mental sejak dini, pembentukan komunitas pendamping, hingga pelatihan bagi guru dan orang tua tentang literasi psikologis remaja.
Upaya ini menuntut kerja sama lintas sektor: dari dunia pendidikan, layanan kesehatan, hingga tokoh masyarakat. Kesehatan mental bukan hanya urusan rumah sakit, tapi tanggung jawab sosial bersama.
Ketika gangguan mental tak lagi dianggap tabu, saat itulah ruang pemulihan terbuka. Di balik angka dan diagnosa, ada generasi yang berjuang dalam diam. Yang mereka butuhkan bukan hanya terapi, tetapi juga telinga yang mendengar, tangan yang menggenggam, dan sistem yang merangkul.
Jika tak dimulai sekarang, kita berisiko kehilangan bukan hanya semangat generasi muda, tapi juga masa depan bangsa.
(Muhammad Syaiful / Unhas.TV)
-1024x682.webp)



-300x225.webp)