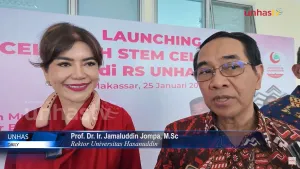MAKASSAR, UNHAS.TV - Cokelat, dengan rasa manis pahitnya yang memikat, bukan sekadar camilan, melainkan warisan budaya yang dijuluki "makanan dewa." Nama ilmiahnya, Theobroma cacao, berasal dari bahasa Yunani yang berarti "makanan para dewa," mencerminkan nilai sakral yang diberikan oleh peradaban kuno.
Sejarah cokelat dimulai sekitar 4.000 tahun lalu di wilayah yang kini menjadi Meksiko dan Amerika Tengah. Suku Olmec, peradaban tertua di Mesoamerika, diyakini sebagai yang pertama mengolah biji kakao. Namun, cokelat benar-benar menjadi pusat budaya pada masa suku Maya dan Aztec (sekitar 250–900 M untuk Maya, dan 1300–1500 M untuk Aztec).
Bagi suku Maya, cokelat bukan sekadar minuman —yang mereka nikmati dalam bentuk pahit dan berbusa— tetapi juga simbol spiritual. Mereka menyebutnya xocolatl (dibaca: shokolatl), yang berarti "air pahit."
Dalam mitologi Maya, kakao dianggap sebagai anugerah dari dewa jagung, Ek Chuah, yang juga pelindung perdagangan. Cokelat digunakan dalam ritual keagamaan, seperti persembahan kepada dewa, upacara pernikahan, dan bahkan sebagai pengganti darah dalam pengorbanan simbolis.
Suku Aztec membawa penghormatan terhadap kakao ke level yang lebih tinggi. Mereka percaya biji kakao adalah hadiah dari Quetzalcoatl, dewa berbulu ular yang mengajarkan kearifan kepada manusia.
Karena nilai sucinya, cokelat hanya dikonsumsi oleh bangsawan, pendeta, dan prajurit dalam upacara. Biji kakao bahkan digunakan sebagai mata uang—satu biji bisa ditukar dengan sebutir telur, dan seratus biji untuk seekor kalkun. Minuman cokelat Aztec, yang dicampur dengan cabai, vanili, atau madu, dianggap memberi kekuatan dan menghubungkan manusia dengan dunia ilahi.
Perjalanan ke Eropa: Dari Sakral ke Sekuler
Cokelat tiba di Eropa pada abad ke-16, dibawa oleh penjelajah Spanyol seperti Hernán Cortés setelah menaklukkan Aztec. Awalnya, cokelat tetap eksklusif, dinikmati oleh bangsawan Spanyol dalam bentuk minuman panas yang dimaniskan dengan gula tebu—penyesuaian dari resep asli Mesoamerika yang pahit.
Gereja Katolik sempat memperdebatkan status cokelat: apakah ia minuman atau makanan, karena ini memengaruhi aturan puasa. Namun, cokelat akhirnya diterima dan bahkan dianggap memiliki khasiat kesehatan, seperti meningkatkan stamina dan melawan kelelahan.
Pada abad ke-17, cokelat menyebar ke Prancis, Inggris, dan Belanda, menjadi simbol kemewahan di kalangan aristokrasi. Rumah-rumah cokelat pertama muncul di London, tempat orang kaya berkumpul untuk menikmati minuman ini. Meski kehilangan konteks sakralnya, cokelat tetap dianggap istimewa, hampir seperti anugerah surgawi bagi mereka yang mampu membelinya.
Revolusi Industri dan Cokelat Modern
Pada abad ke-19, cokelat bertransformasi dari minuman elit menjadi makanan yang bisa dinikmati semua orang. Penemuan mesin press kakao oleh Casparus van Houten pada 1828 memungkinkan pemisahan mentega kakao dari bubuk kakao, menghasilkan cokelat yang lebih halus dan murah.
Ini membuka jalan bagi cokelat padat pertama, diciptakan oleh perusahaan Inggris J.S. Fry & Sons pada 1847.
Pada 1875, Daniel Peter dari Swiss mencampurkan susu bubuk (ciptaan Henri Nestlé) dengan cokelat, melahirkan cokelat susu yang lembut dan creamy—versi yang kini mendominasi pasar. Merek-merek seperti Cadbury, Lindt, dan Hershey mulai memproduksi cokelat secara massal, menjadikannya camilan sehari-hari. Namun, jejak "makanan dewa" tetap ada dalam cara cokelat dipasarkan: sebagai kenikmatan yang nyaris mistis, mampu memanjakan jiwa.
Cokelat dan Simbolisme Ilahi di Era Modern
Hingga kini, cokelat tetap mempertahankan aura istimewanya. Dalam iklan, cokelat sering digambarkan sebagai pengalaman yang mendekati transendental—seperti "surga di setiap gigitan."
Ini bukan kebetulan, melainkan jejak dari sejarah panjangnya sebagai sesuatu yang suci. Festival cokelat di seluruh dunia, seperti Salon du Chocolat di Paris, bahkan terasa seperti perayaan untuk menghormati warisan kakao.
Namun, cokelat modern juga menghadapi tantangan etis. Produksi kakao sering dikaitkan dengan deforestasi, eksploitasi tenaga kerja, dan perdagangan yang tidak adil. Untuk menghormati "makanan dewa" ini, banyak produsen kini beralih ke cokelat organik dan fair trade, memastikan bahwa kenikmatan cokelat tidak mengorbankan manusia atau alam.
Dari minuman ritual suku Maya dan Aztec hingga camilan global yang kita kenal sekarang, cokelat telah menempuh perjalanan panjang. Julukan "makanan dewa" bukan sekadar metafora, melainkan cerminan dari nilai spiritual dan budaya yang melekat padanya selama ribuan tahun.
Setiap gigitan cokelat adalah pengingat akan warisan Quetzalcoatl, Ek Chuah, dan peradaban yang melihat kakao sebagai jembatan menuju dunia ilahi. Jadi, lain kali Anda menikmati sebatang cokelat, ingatlah: Anda sedang merasakan sepotong sejarah yang benar-benar surgawi.(*)






-300x169.webp)