MAKASSAR, UNHAS.TV - Kata "insinyur" di Indonesia berasal dari kata Belanda "ingenieur" dan akhirnya dari bahasa Latin "ingeniator" yang berarti pencipta atau inovator.
Istilah ini merujuk pada insinyur profesional. Sejarah insinyur di Indonesia sangat terkait dengan masa kolonial, perjuangan kemerdekaan, dan perkembangan negara modern. Artikel ini menelusuri evolusi profesi insinyur di Indonesia, menyoroti tonggak sejarah, institusi, dan kontribusi utama.
Era Kolonial: Abad 16–19
Konsep teknik di Indonesia sudah ada sebelum istilah "insinyur" digunakan secara resmi. Pada masa pra-kolonial, kerajaan seperti Majapahit dan Sriwijaya menunjukkan keahlian teknik melalui sistem irigasi, pembangunan candi (misalnya Borobudur dan Prambanan), serta teknologi maritim. Namun, peran insinyur yang terformalisasi muncul bersamaan dengan kolonisasi Eropa.
Di bawah kekuasaan Belanda (1602–1945), Perusahaan Hindia Timur Belanda (VOC) memperkenalkan praktik teknik Barat untuk mendukung perdagangan dan infrastruktur. Insinyur Belanda, yang dikenal sebagai "ingenieurs," berperan penting dalam membangun benteng, kanal, dan pelabuhan, seperti di Batavia (sekarang Jakarta).
Insinyur ini sebagian besar adalah orang Eropa yang dilatih di Belanda, fokus pada kepentingan kolonial seperti perdagangan dan pertahanan.
Pada abad ke-19, Belanda mendirikan sekolah teknik pertama untuk melatih asisten lokal dan Eurasia dalam tugas-tugas teknik dasar.
Kultuurstelsel (Sistem Tanam Paksa) membutuhkan infrastruktur luas, termasuk jalan, jembatan, dan sistem irigasi, yang meningkatkan permintaan tenaga terampil. Namun, orang Indonesia jarang diberi gelar insinyur karena pendidikan tinggi dan pengakuan profesional hanya diperuntukkan bagi orang Eropa.
Awal Abad 20: Kebangkitan Insinyur Pribumi
Awal abad ke-20 menjadi titik balik dengan munculnya intelektual Indonesia dan dorongan untuk pendidikan. Belanda mendirikan Technische Hoogeschool (Sekolah Tinggi Teknik) di Bandung pada tahun 1920, yang kemudian menjadi Institut Teknologi Bandung (ITB).
Institusi ini sangat penting dalam melatih generasi pertama insinyur Indonesia. Awalnya, penerimaan siswa terbatas, dan kurikulumnya meniru sekolah teknik Belanda, berfokus pada teknik sipil, mekanik, dan listrik.
Salah satu insinyur Indonesia awal yang terkenal adalah Ir. Soekarno, presiden pertama Indonesia, yang lulus dari Technische Hoogeschool pada tahun 1926 dengan gelar di bidang teknik sipil.
Pendidikan dan visi Soekarno untuk pembangunan infrastruktur mencerminkan aspirasi orang Indonesia untuk menguasai teknik demi kemajuan nasional. Tokoh lain seperti Ir. Roosseno Soerjohadikoesoemo, seorang insinyur sipil, juga berkontribusi pada teknik konstruksi modern.
Pada periode ini, insinyur Indonesia mulai membentuk organisasi profesi. Pada tahun 1933, Vereeniging van Indische Ingenieurs (Asosiasi Insinyur Hindia) didirikan sebagai wadah kolaborasi insinyur Eropa dan Indonesia. Namun, hierarki rasial dan kolonial membatasi pengaruh insinyur pribumi.
Pendudukan Jepang dan Kemerdekaan (1942–1949)
Pendudukan Jepang (1942–1945) mengganggu pendidikan formal tetapi mempercepat keterlibatan insinyur Indonesia dalam proyek infrastruktur. Jepang mengandalkan keahlian lokal untuk memelihara jalan, rel kereta, dan fasilitas militer, memberikan pengalaman praktis bagi insinyur Indonesia.
Setelah Proklamasi Kemerdekaan pada tahun 1945, insinyur memainkan peran penting dalam perjuangan mempertahankan negara baru.
Banyak insinyur membantu membangun infrastruktur darurat, memperbaiki fasilitas yang rusak akibat perang, dan mendukung upaya gerilya.
Pendirian Universitas Indonesia pada tahun 1947 dan kelangsungan operasi institut di Bandung memberikan dasar bagi pendidikan teknik selama tahun-tahun penuh gejolak perjuangan kemerdekaan.
Insinyur Indonesia menjadi simbol kemandirian, seiring bangsa muda ini berupaya mengurangi ketergantungan pada keahlian asing.
Pasca-Kemerdekaan: Pembangunan Bangsa dan Profesionalisasi (1950–1980an)
Era pasca-kemerdekaan adalah masa keemasan bagi insinyur Indonesia, karena pemerintah memprioritaskan infrastruktur dan industrialisasi.
Di bawah kepemimpinan Soekarno, proyek ambisius seperti Bendungan Jatiluhur, Kereta Api Ambarawa, dan Monumen Nasional (Monas) menunjukkan kemampuan insinyur Indonesia.
Pemerintah juga mendirikan fakultas teknik baru di universitas seperti Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) untuk memenuhi kebutuhan insinyur.
Pada tahun 1959, Persatuan Insinyur Indonesia (PII) didirikan untuk menyatukan dan memprofesionalkan komunitas insinyur.
PII berperan dalam menstandarkan kualifikasi, memperjuangkan hak insinyur, dan memfasilitasi kolaborasi dengan badan teknik internasional. Gelar "Ir." (Insinyur) menjadi tanda kehormatan yang diberikan kepada lulusan program teknik terakreditasi.
Selama era Orde Baru (1966–1998) di bawah Presiden Soeharto, Indonesia mengejar modernisasi cepat. Insinyur berada di garis depan proyek seperti Jalan Raya Trans-Sumatra,
Pabrik Baja Krakatau, dan program elektrifikasi pedesaan. Pemerintah juga mengirim insinyur ke luar negeri untuk pelatihan lanjutan, terutama ke Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa, untuk memperoleh keahlian di bidang baru seperti teknik kimia dan dirgantara.
Era Modern: Globalisasi dan Tantangan (1990an–Sekarang)
Akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21 menyaksikan insinyur Indonesia beradaptasi dengan globalisasi dan kemajuan teknologi. Krisis Keuangan Asia 1997 sementara memperlambat pembangunan infrastruktur, tetapi upaya pemulihan di bawah pemerintahan berikutnya menghidupkan kembali peran insinyur.
Proyek besar seperti MRT Jakarta, kereta cepat, dan bandara baru menyoroti keahlian insinyur Indonesia modern.
PII memperkenalkan proses sertifikasi yang lebih ketat, selaras dengan standar internasional seperti ASEAN Federation of Engineering Organisations (AFEO). Gelar "Ir." tetap menjadi tanda prestise, meskipun adopsi global gelar seperti "Professional Engineer" (P.Eng.) memicu diskusi tentang standarisasi.
Saat ini, insinyur Indonesia menghadapi tantangan baru, termasuk pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim, dan transformasi digital.
Bidang seperti energi terbarukan, kecerdasan buatan, dan infrastruktur hijau semakin menonjol. Insinyur wanita, yang secara historis kurang terwakili, juga mulai menorehkan prestasi, dengan tokoh seperti Tri Rismaharini, seorang insinyur sipil dan mantan wali kota Surabaya, yang mendobrak batasan.
Kesimpulan
Sejarah insinyur di Indonesia mencerminkan perjalanan bangsa dari penjajahan kolonial menuju negara modern. Dari membangun benteng kolonial hingga merancang kota berkelanjutan, insinyur Indonesia telah berperan penting dalam membentuk lanskap fisik dan ekonomi negara. Seiring Indonesia terus berkembang sebagai pemain global, insinyur tetap menjadi pilar kemajuan, mewujudkan inovasi, ketahanan, dan komitmen terhadap pembangunan nasional.(*)

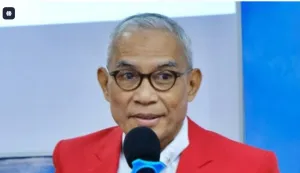


-300x159.webp)







