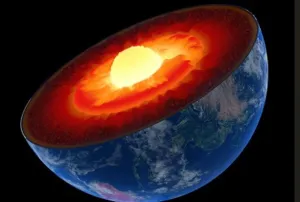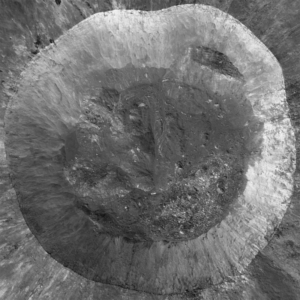PARIS, UNHAS.TV. Tiga tahun setelah kemunculan ChatGPT, wacana tentang kecerdasan buatan berubah drastis. Dari euforia teknologi, perbincangan publik kini dipenuhi nada muram: peringatan tentang “risiko eksistensial”, kehancuran peradaban, bahkan kepunahan manusia akibat AI yang tak terkendali. Namun di balik kecemasan kosmik itu, tersembunyi ketakutan yang jauh lebih membumi—dan sangat politis: kecemasan kelas sosial.
Artikel karya Tony Gheeraert yang dimuat di l'L'Humanité edisi Prancis ( Intelligence artificielle : l’IA, une apocalypse en col blanc ?, 2 novembre 2025 ) menyingkap lapisan itu dengan telanjang. Ketakutan terhadap AI, tulis Gheeraert, terutama melanda kelompok yang selama puluhan tahun relatif aman dari badai otomasi: para elite intelektual dan pekerja kerah putih;
- dosen dan peneliti
- jurnalis dan penulis
- pegawai negeri dan birokrat
- pengacara, akuntan, konsultan
- manajer dan eksekutif
- profesional IT, analis data, desainer
Demokratisasi yang Tidak Disambut Sukacita
Ketika OpenAI membuka akses luas terhadap AI generatif pada akhir 2022, dunia terguncang. Untuk pertama kalinya, alat yang mampu menulis, menganalisis, menyusun argumen hukum, hingga menulis kode komputer tersedia gratis. AI memberi suara kepada mereka yang selama ini tersingkir karena keterbatasan bahasa, pendidikan, atau akses. Ia menjadi guru, penulis umum, pengacara pemula, dan programmer dasar—fungsi-fungsi yang sebelumnya dimonopoli kelompok terdidik.
Secara logis, ini adalah kabar baik: demokratisasi pengetahuan dan keterampilan. Namun kegembiraan itu nyaris tak pernah benar-benar terjadi. Yang muncul justru kepanikan. Robot dituduh “berhalusinasi”, siswa dicurigai curang, sementara nyaris tak ada refleksi jujur bahwa para guru, peneliti, dan profesional juga diam-diam memanfaatkan alat yang sama.
Tak lama kemudian, nada diskusi mengeras. Sejumlah ilmuwan ternama tampil di media global memperingatkan “bahaya peradaban”. Geoffrey Hinton dan Yoshua Bengio—dua tokoh besar AI—menyuarakan kekhawatiran serius tentang masa depan manusia. Laporan spekulatif seperti “AI 2027” beredar luas. Di sisi lain, publik diarahkan untuk merasa bersalah atas konsumsi energi AI. Segala cara ditempuh untuk menahan gelombang.
Padahal, kontrasnya mencolok: di satu sisi, peningkatan kapasitas bertindak bagi mayoritas manusia; di sisi lain, nubuat kehancuran yang berulang-ulang. Pertanyaannya: mungkinkah kepanikan ini digerakkan—secara sadar atau tidak—oleh kepentingan korporatis dan profesional?
Ketika Mesin Menjadi Pesaing
Dalam jangka pendek, AI terutama mengganggu mereka yang hidup dari penguasaan bahasa, simbol, dan pengetahuan. Peneliti, jurnalis, politisi, pengacara, konsultan, dosen, pengembang, hingga investor—kelompok yang jarang merasa rapuh—tiba-tiba berhadapan dengan pesaing yang tak terbayangkan sebelumnya: mesin yang mampu berbicara dan menulis.
Yang tua menghitung sisa tahun menuju pensiun. Yang muda bertanya dengan cemas: pekerjaan manusia apa yang masih bernilai simbolik—dan bergaji layak—di masa depan?
Namun sejarah menunjukkan, ini bukan kali pertama teknologi mengguncang martabat kerja. Pada 1980–1990-an, mekanisasi industri menghancurkan jutaan pekerjaan kelas pekerja di Eropa. Ketika tanur baja Lorraine di Prancis padam—dari Longwy hingga Gandrange—tak ada teriakan “kiamat”. Yang terdengar justru jargon “transformasi yang tak terelakkan”. Saat pabrik Renault Billancourt ditutup pada 1992, sosiolog Pierre Bourdieu mendokumentasikan akhir sebuah dunia bagi kelas rakyat, tanpa menyebutnya sebagai akhir dunia.
Di Vilvoorde, Belgia, pada 1997, pemecatan massal dianggap harga wajar globalisasi. Alain Minc berbicara tentang “globalisasi yang membahagiakan”. Media arus utama merasionalisasi penderitaan dengan statistik dingin: buruh yang tersisa disebut “tua, tak terampil, migran, buta huruf”. Kemanusiaan direduksi menjadi catatan kaki sejarah. Masa depan, kata mereka, ada di sektor jasa dan digital.
Kita tahu akibat kebutaan itu: ketimpangan, keterasingan, dan krisis demokrasi.
Ketakutan Baru, Reaksi Berbeda
Kini, ketika otomasi menyapu sektor jasa—bahkan manajemen—nada berubah. Tak ada lagi pembicaraan tentang “keniscayaan”. Yang terdengar adalah tuntutan pembatasan, larangan, dan sanksi. Gheeraert menyindir: kecil kemungkinan perawat, tukang roti, tukang ledeng, atau buruh bangunan merasakan kecemasan eksistensial yang sama dengan kaum intelektual terhadap AI.
Apakah kini giliran pekerja intelektual yang diperintahkan: “beradaptasi atau lenyap”?
Kesalahan lama tak boleh diulang. Teknologi telah lama dipuja bak berhala, sementara kebenaran sederhana dilupakan: nilai hanya diciptakan oleh kerja manusia yang hidup, sebagaimana ditegaskan Karl Marx.
Ancaman Sebenarnya: Konsentrasi Kekuasaan
Masalahnya bukan AI itu sendiri. Ancaman sejatinya adalah penguasaan AI oleh segelintir perusahaan, dengan agenda ideologis yang tak transparan, yang menambang karya intelektual dan artistik umat manusia secara massal—tanpa demokrasi—lalu merekayasa ulang kerja dan pengetahuan.
Skenario “AI gila menguasai planet” hanyalah fiksi. “Kiamat demokratis” justru telah berlangsung: konsentrasi kekuasaan teknis, ketergantungan pada algoritma privat, dan memudarnya penilaian manusia.
Jalan Keluar yang Nyata
Gheeraert menawarkan langkah konkret—bukan nubuat:
- hak atas intervensi manusia dalam keputusan penting;
- audit independen terhadap sistem AI dengan kewenangan menghentikan penyimpangan;
- kewajiban perundingan di tempat kerja sebelum penerapan AI dan larangan pemecatan otomatis;
- pembangunan commons digital: dana publik untuk model dan data terbuka bagi sekolah, rumah sakit, dan UKM;
- perpustakaan data yang etis dan terlindungi;
- royalti wajib bagi pers, riset, dan karya kreatif;
dan yang terpenting, investasi besar pada keterampilan manusia: membaca, menulis, bernalar, merawat, dan mengambil keputusan.
Mesin boleh membantu. Ia tak boleh menggantikan. (*)
 undefined
undefined