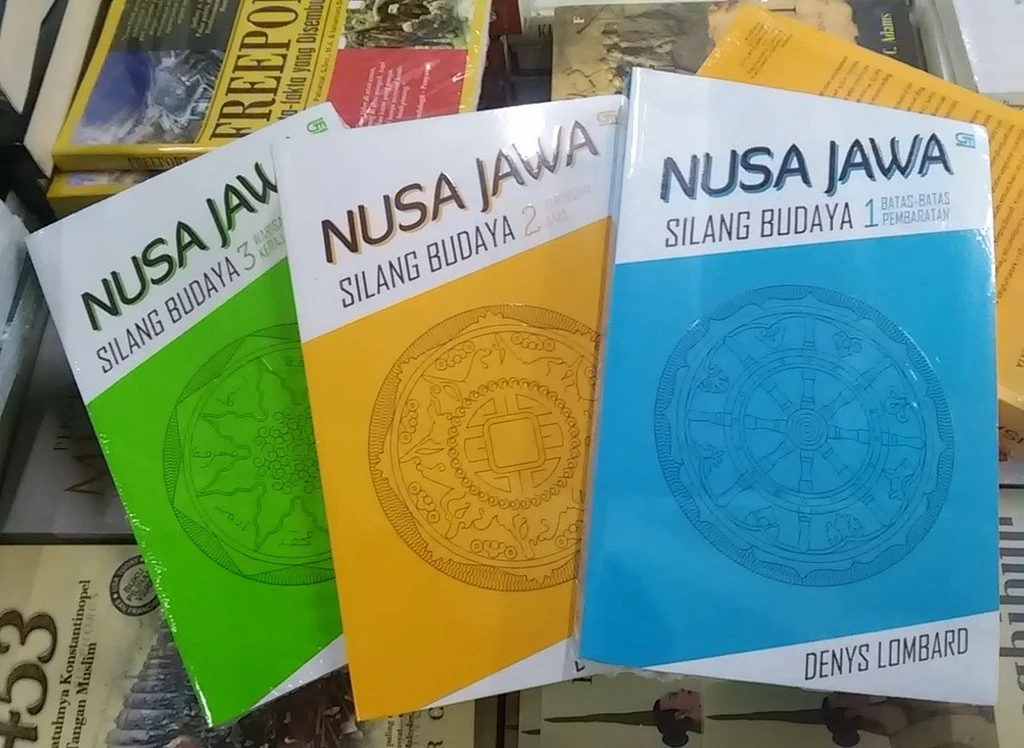
Sebuah kombinasi langka di Asia Tenggara, singkat namun berkilau. Di satu sisi, Makassar memelihara denyut ekonomi maritim, menghubungkan pulau-pulau rempah dengan jalur sutra samudra. Di sisi lain, ia membuka diri pada percakapan tentang kosmos, pemerintahan, dan dunia yang tak lagi sebatas cakrawala Bugis Makassar.
Lombard melihat Makassar sebagai kota yang menampung dua arus besar peradaban: arus dagang yang menciptakan kekuatan material, dan arus gagasan yang menumbuhkan kebesaran intelektual.
Jika Malaka adalah mercusuar emas dan Aceh lentera ilmu agama, maka Makassar adalah jendela yang menatap ke dua arah sekaligus: ke pasar dunia, dan ke langit penuh bintang.
Dalam pandangan Lombard, justru di persilangan itulah Makassar menemukan keistimewaannya. Ia bukan sekadar titik di peta jalur rempah, melainkan laboratorium kosmopolitanisme yang lahir dari laut dan pikiran. Sebuah kota yang memperlihatkan betapa mungkin bagi bangsa maritim untuk merangkul dunia tanpa kehilangan dirinya.
Namun sejarah juga membawa luka. Tahun 1669, Benteng Somba Opu runtuh, dan kota itu jatuh ke tangan VOC. Bersamanya hilang bukan hanya pelabuhan bebas, melainkan juga sebuah mimpi: bahwa ada ruang di timur Nusantara yang bisa menjadi penyeimbang, bukan hanya dalam rempah, tapi juga dalam ilmu.
Sejak saat itu, ingatan tentang Makassar perlahan tenggelam. Lombard menuliskannya dengan nada getir. “La chute de Makassar signifia la fin d’un monde: celui d’un port ouvert, d’un carrefour de cultures, effacé par le monopole colonial.”
“Kejatuhan Makassar berarti akhir dari sebuah dunia: dunia sebuah pelabuhan terbuka, sebuah simpang peradaban, yang dihapus oleh monopoli kolonial.”
Dan mungkin, di situlah tragedi itu menemukan maknanya: bahwa sebuah bangsa bisa membuka pintu pada dunia, tetapi pintu itu bisa ditutup paksa oleh meriam dan kekuasaan.
Prof. Nasaruddin menutup kisah itu dengan nada getir. Ia mengingatkan, banyak harta karun intelektual Bugis Makassar kini justru tersimpan jauh di Leiden. Manuskrip, catatan niaga, dan jejak literasi leluhur seakan tercerabut dari tanah asalnya.
Generasi baru yang ingin merasakan kembali gairah dagang dan intelektual nenek moyangnya harus menempuh ribuan kilometer, sekadar untuk menyentuh lembaran-lembaran yang dahulu lahir dari pelabuhan Somba Opu.
Ada kesedihan yang tak bisa ditutupi: bahwa warisan kejayaan Makassar kini lebih mudah diakses di negeri jauh, ketimbang di tanah tempat ia pernah berakar.
Sebab sejarah, seperti laut, selalu menyimpan dua wajah: ia bisa menjadi dermaga bagi perjumpaan, atau karang tempat kapal-kapal patah.
*Penulis adalah blogger, peneliti, dan digital strategist. Lulus kuliah di Unhas, UI, dan Ohio University. Kini tinggal di Bogor, Jawa Barat











