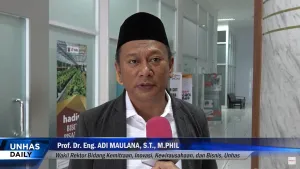Fadli Ilham
JIKA ingin menemukan jiwa-jiwa kemanusiaan yang bercahaya, maka lihatlah orang-orang yang selalu memanggul wajahnya penuh percaya diri--bukan tertunduk malu. Tapi dengan keberanian dan suara lantang untuk tanah adat, untuk lingkungan dan untuk ruang hidup anak cucu mereka di masa mendatang.
Mereka adalah 11 warga Maba Sangaji di Haltim, Maluku Utara. Kini dinyatakan bersalah dalam kasus penolakan praktik pertambangan yang dinilai merusak lingkungan dan merugikan rakyat. Sulit untuk membenarkan putusan tersebut, di tengah gelombang dukungan moral dan gerakan nurani rakyat dari berbagai penjuru.
Sikap yang lahir dari civil society sejak awal terus bergaung. Mereka mengecam; atas nama pejuang lingkungan, 11 warga Maba Sangaji harus dibebaskan. Dukungan massa dan titik pergelaran aksi meluas di berbagai tempat.
Tuntutan keadilan itu tak bertepi. Di altar kekuasaan, amarah terus diserukan. Meski nyaris diabaikan. Kekuatan akar rumput itu laksana cahaya nurani; bergerak dan terpanggil dari pantulan jiwa-jiwa kebajikan.
Sedangkan mereka yang memegang kekuasaan terkesan berada di ruang hampa. Suara-suara ketidakadilan nyaris tersumbat. Mereka lalu lalang dengan gagah, tapi menutup mata dan telinganya di tengah keriuhan aspirasi.
Mereka yang berkuasa kehilangan kewarasan dan jauh dari yang diperkenalkan Thomas Hobbes, John Locke, dan JJ Rousseau tentang teori kontrak sosial. Kerangka teori ini menjelaskan, sebagian hak warga diserahkan kepada suatu otoritas untuk dikelola secara martabat. Mereka adalah penguasa yang bertanggung jawab sebagai pelayan keadilan yang lahir dari rakyatnya.
Pendekatan ini memicu pertanyaan kritis pada kasus tersebut. Dalam berbagai bentuk tuntutan dari civil society, kekuasaan terkesan nirempati. Kesungguhan mereka sebagai bagian yang menyelenggarakan kekuasaan atas daulat rakyat justru mengendap dalam sistem demokrasi. Sebaliknya, masyarakat akar rumput yang terpaut menyelenggarakan simpul-simpul kekuatan.
Mereka yang berwenang dalam kekuasaan, lebih terkesan bekerja untuk dibungkam. Terlepas dari kepentingan apapun, dukungan moral civil society pun tidak dielakkan corong kekuasaan sebagai bentuk aspiratif yang menghendaki terwujudnya keadilan.
Dalam konteks ini, bukan lagi pada persoalan kemunduran demokrasi. Tapi rakyat seolah-olah kembali hidup alamiah tanpa ada suatu otoritas yang berwenang menyelenggarakan keadilan, seperti yang ditegaskan dalam konsep kontrak sosial sebelumnya, bahwa rakyat memiliki jaminan setelah sebagian kebebasannya telah diberikan.
Kekuasaan saat ini dapat digambarkan seperti mesin yang berlindung dibalik batas kewenangan. Mereka tidak tergerak atas nama kemanusiaan yang di dalamnya bersemayam prinsip keadilan. Tapi kepentingan politik yang menjegal pada lingkaran oportunis.
Gus Dur dalam ungkapannya "Yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan." Dalam kaitanya dengan kasus pejuang lingkungan, tindakan kemanusiaan sangat masif ditunjukan dari civil society melalui dukungan dan gerakan moral yang dilakukan secara organisir.
Mereka yang berwenang dituntut memiliki kepekaan untuk menunjukan sikapnya di tengah rakyat yang tak pernah henti menyeru keadilan. Tak ayal jika mereka layak disandingkan dengan mesin, tidak memiliki nurani dan bergerak pada kepentingan-kepentingan yang dikendalikan.
Daya kritis masyarakat untuk memandang kekuasaan harus diperluas, bahwa mereka yang secara sungguh-sungguh bekerja tidak hanya diukur dari batas ruang tertentu, tapi niscaya berada dalam ruang-ruang kesempitan hidup rakyatnya dan ketidakadilan yang secara nyata mengapung di permukaan publik.
Keadilan yang Dikehendaki
Keadilan adalah kebahagiaan sesuai kebajikan. Walaupun diakui bahwa ideal ini cukup sulit bisa diwujudkan sepenuhnya. Seyogyanya, memperjuangkan keadilan merupakan lahan subur persemaian kemanusiaan --datang dari orang yang bersiteguh untuk hidup dalam kejujuran dan kesederhanaan.
Kasus yang melibatkan pejuang lingkungan dengan industri pertambangan, cukup sulit untuk mendefinisikan kriteria yang dipersyaratkan. Terlebih lagi, gagasan tentang keadilan distributif berdasarkan kebajikan gagal membedakan antara kelayakan moral.
Kelayakan moral di tubuh kekuasaan tidak sepenuhnya mendistribusi keadilan secara utuh. Tapi berkelindang dengan institusi yang menentukan nasib hukum yang berlawanan dengan nurani rakyat. Ini merupakan cara kerja dengan berlindung dibalik pengaturan yang membenarkan sistem berjalan berdasarkan selera kekuasaan.
Sedangkan yang diharapkan dalam struktur sosial adalah terciptanya tatanan masyarakat tertata rapi, yakni sebuah masyarakat di mana berbagai lembaga adil adanya dan fakta ini diakui publik.
Pendekatan ini menegaskan bahwa institusi hukum sekalipun bukan semata-mata dapat menjelma sebagai ratu adil, tapi ada ruang-ruang dimana kepentingan dan siasat melindungi kasta tertentu.
Sejalan dengan gagasan itu, Henry Sidwick seorang filsuf yang terkenal dengan karyanya The Methods of Ethics mengemukakan hukum dan lembaga bisa sama-sama hadir namun tidak mewujudkan keadilan. Memperlakukan kasus-kasus serupa dengan cara yang sama tidak menjadi jaminan yang mencukupi keadilan substantif.
Prinsip keadilan substantif adalah tidak ada kontradiksi dalam mendiskriminasi masyarakat kasta dalam benturan konflik dengan korporasi pertambangan. Kendati keadilan sebagai regulatif, menyingkirkan berbagai macam bentuk ketidakadilan. Sebab, jika diasumsikan bahwa berbagai lembaga adalah adil, maka otoritasnya harus objektif dan tidak dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan yang bergelayutan.
Buku Teori Keadilan karya John Rawls menguraikan dua prinsip keadilan yang cukup relevan dengan kasus yang dialami 11 warga Maba Sangaji. Prinsip pertama; bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang.
Dalam penjelasan John Rawls, mereka membagi antara aspek-aspek sistem sosial yang mendefinisikan dan menjamin kebebasan warga negara dan aspek yang menunjukan ketimpangan sosial-ekonomi.
Kebebasan dasar warga negara adalah kebebasan politik, bersama dengan kebebasan berbicara; kebebasan berkeyakinan dan kebebasan berpikir; kebebasan seseorang seiring dengan kebebasan untuk mempertahankan hak milik (personal); dan kebebasan dari penangkapan sewenang-wenang sebagaimana didefinisikan oleh konsep rule of law. Bagi John, dalam prinsip keadilan ini diharuskan setara, karena warga suatu masyarakat yang adil mempunyai hak-hak dasar yang sama.
Dari berbagai pendekatan, perspektif rakyat menyaksikan betapa rapuhnya kekuasaan menyemai keadilan yang notabenenya menjadi kehendak terakhir atas impian para pejuang bangsa. Soekarno lebih awal telah mengingatkan itu, bahwa keadilan sebagai revolusi terakhir. Kendati kekuasaan saat ini tidak menangkap itu sebagai sebuah tuntutan keadilan yang harus dikehendaki dalam berbagai aspek.(*)

Penulis adalah Koordinator I Forum Komunikasi Pemuda (FKP) Maluku Utara dan Mahasiswa S3 FISIP Universitas Hasanuddin (Unhas)
 Ilustrasi tambang
Ilustrasi tambang