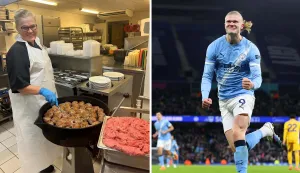oleh: Mursalim Nohong*
Rasanya pantas jika jargon “Sidrap menyala, abangku” disematkan untuk menggambarkan realitas sosial terkini di kabupaten yang terletak di jantung Sulawesi Selatan ini.
Bukan karena geliat pembangunan atau prestasi anak mudanya yang mencuri perhatian nasional, tetapi karena nyaris setiap hari ruang imajinasi publik dijejali berita tentang maraknya sindikat penipuan daring—yang oleh masyarakat lokal dikenal sebagai passobis.
Lebih dari sekadar penyakit masyarakat, praktik 4S (sobis, sabu, sabung, dan seks bebas) kini seolah menjelma menjadi gaya hidup baru, terutama di kalangan generasi Z.
Bagi sebagian anak muda, menjadi pelaku sobis bukanlah aib, melainkan jalan hidup. Di tengah derasnya arus digitalisasi dan tekanan ekonomi, sobis menawarkan jalan pintas yang menggoda: cepat, instan, dan—sayangnya—tak jarang tanpa konsekuensi berarti.
Yang mencemaskan, kekuatan para pemegang saham di balik jaringan ini tak mudah digoyahkan. Mereka bukan hanya mampu merangsek hingga ke jantung birokrasi dan keamanan lokal, tetapi juga sanggup menumbangkan otoritas.
Adagium baru pun muncul dan dipercaya luas: “Siapa pun pejabat, terutama aparat keamanan, yang berani menegur atau mengganggu praktik 4S, akan segera dipindahkan atau dinonjobkan.”
Namun, sekuat-kuatnya jejaring ini, ada celah yang akhirnya terbuka. Pada Kamis, 24 April 2025, tim dari Kodam XIV/Hasanuddin menggerebek dan menangkap 40 pelaku passobis di Kabupaten Sidrap. Mereka beraksi dengan mencatut nama pejabat Kodam untuk melancarkan penipuan.
Penggerebekan ini menjadi peristiwa penting, dan paling tidak mencerminkan tiga hal.
Pertama, passobis bukan mitos. Ia nyata, terorganisir, dan melibatkan kelompok-kelompok anak muda dengan struktur anggota mencapai 50 orang per kelompok—generasi Z yang seharusnya menjadi penopang bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045.
Kedua, masuknya TNI dalam operasi ini menunjukkan betapa sektor keamanan konvensional tampak kurang tanggap, atau bahkan gamang, dalam menindak kasus yang sudah lama membentuk ekosistem ilegal tersendiri.
Ketiga, keberanian para pelaku untuk terus beroperasi secara terang-terangan menunjukkan bahwa sanksi yang ada belum cukup menimbulkan efek jera. Rasa aman yang ditawarkan oleh lemahnya penegakan hukum justru memperkuat keyakinan bahwa sobis bukanlah tindakan kriminal, melainkan alternatif profesi.
Untuk memahami lebih dalam akar sosiologis dari fenomena ini, kita dapat merujuk pada teori Fraud Diamond yang dikembangkan Wolfe dan Hermanson (2004) sebagai pengembangan dari Fraud Triangle milik Cressey (1953).
Teori ini menyebut empat elemen pendorong utama seseorang melakukan kecurangan: tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kemampuan.
Tekanan bisa berupa gaya hidup konsumtif, utang, atau tuntutan ekonomi keluarga. Kesempatan muncul dari lemahnya sistem pengawasan dan budaya permisif. Rasionalisasi beroperasi melalui pembenaran diri: "Semua orang juga lakukan ini." Sementara kemampuan meliputi literasi digital, keterampilan komunikasi, hingga kecakapan menyembunyikan jejak.
Sebuah studi oleh Sri Ulfa dkk (2020) terhadap 100 generasi Z di Sidrap yang terpapar praktik passobis mengonfirmasi semua elemen ini. Dari hasil riset ditemukan, sebanyak 79% pelaku melakukan sobis karena tekanan gaya hidup konsumtif, disusul faktor sulitnya mencari pekerjaan (49%).
Sementara itu, 83% menyebut lemahnya pengawasan sebagai peluang utama, dan 84% mengakui sikap permisif masyarakat turut memperkuat keberanian mereka.
Ironisnya, 80% pelaku merasionalisasi bahwa sobis adalah pekerjaan sah karena menghasilkan uang dan dianggap umum dilakukan. Namun secara moral dan hukum, mayoritas mengakui bahwa perbuatan itu salah: 97% menyatakan sobis tidak etis, dan 99% mengakuinya sebagai tindakan ilegal. Mereka tahu, tapi tetap melakukannya—karena mampu.
Fakta-fakta ini memberi sinyal darurat. Fenomena sobis bukan sekadar tindakan kriminal, tapi gejala sosial yang kompleks dan berakar. Karena itu, solusinya pun harus sistemik.
Mulai dari rumah dan lingkungan terdekat, pengawasan perlu diperkuat. Tekanan ekonomi bisa diatasi lewat edukasi literasi finansial dan dukungan kesehatan mental. Kesempatan harus diminimalisir lewat penguatan keamanan siber dan regulasi akses data.
Rasionalisasi perlu dilawan melalui kampanye publik yang menyasar integritas digital, dan kemampuan generasi muda perlu disalurkan ke ruang-ruang produktif—entah lewat startup, pendidikan teknologi, atau gerakan sosial.
Tentu, Sidrap bisa menyala dengan cara lain. Bukan karena skema penipuan yang merajalela, tetapi karena daya juang anak mudanya untuk menyalakan harapan dan masa depan.
*Penulis adalah Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unhas, putra kelahiran Sidrap, Sulawesi Selatan.