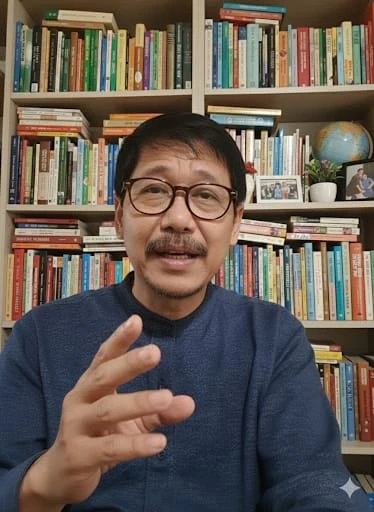Oleh: Muliadi Saleh (Esais Reflektif dan Arsitek Kesadaran Sosial)
Dalam sejarah Indonesia, ada tokoh yang hidupnya bukan sekadar deret peristiwa, melainkan peta nilai. Salah satu di antaranya adalah Buya Hamka. Seorang ulama, sastrawan, pemikir, dan pendidik .
Ia tidak hanya menulis buku, tetapi menanam makna; tidak sekadar berdakwah, tetapi membangun kesadaran. Perjalanan hidupnya adalah narasi panjang tentang keteguhan, keluasan ilmu, dan keberanian moral di tengah zaman yang sering gaduh oleh kepentingan.
Nama Buya Hamka sesungguhnya adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah, lahir di Sungai Batang, Maninjau, Sumatera Barat. Nama HAMKA bukan sekadar singkatan teknis, melainkan identitas intelektual yang lahir dari perjalanan pemikirannya.
Ia memilih dan kemudian dikenal luas dengan nama ringkas itu bukan untuk memudahkan ingatan semata, tetapi sebagai penanda era. Penegasan bahwa dakwah, sastra, dan pemikiran Islam harus hadir dekat dengan masyarakat, komunikatif, dan membumi.
HAMKA menjadi simbol pertemuan antara ulama dan sastrawan, antara tradisi surau dan dunia modern, antara teks dan konteks. Nama itu akhirnya menjelma lebih besar dari dirinya sendiri. Ia menjadi penanda zaman hingga kini. Gema pemikirannya tetap hidup dalam ingatan kolektif bangsa.
Buya Hamka lahir dari rahim tradisi Minangkabau yang kuat: adat, agama, dan intelektualitas. Namun ia tidak berhenti sebagai pewaris tradisi. Ia mengolahnya. Pendidikan formalnya terbatas, tetapi kecintaannya pada ilmu tak berbatas.
Ia belajar dari kitab, dari perjalanan, dari pergaulan lintas bangsa, dan dari pergulatan batin sendiri. Dari sana lahir karya-karya monumental, diantaranya : Tafsir Al-Azhar, Di Bawah Lindungan Ka’bah, Tenggelamnya Kapal Van der Wijck, yang menjembatani agama, sastra, dan kemanusiaan.
Pelajaran paling penting dari hidup Buya Hamka adalah keberanian untuk jujur pada nurani. Ia pernah dipenjara bukan karena kejahatan, tetapi karena perbedaan sikap politik. Penjara itu tidak memenjarakan pikirannya. Justru di balik jeruji, ia menulis tafsir dan menyapa langit dari ruang sempit.
Dari peristiwa itu kita belajar bahwa intelektual sejati tidak tunduk pada kekuasaan, tetapi pada kebenaran. Ilmu tidak boleh menjadi pelayan kekuasaan, melainkan penuntun akal dan penjaga etika publik.
Buya Hamka juga mengajarkan keluasan hati. Ketika ia memiliki kesempatan membalas luka sejarah, ia memilih memaafkan. Ia menunjukkan bahwa kebesaran jiwa adalah puncak spiritualitas.
Dalam dunia hari ini dimana kondisi mudah menyulut kebencian, cepat menghakimi, dan gemar memecah belah, sikap Buta Hamka terasa kian relevan.
Kita hidup di era polarisasi dimana agama ditarik ke politik praktis, identitas diperdagangkan, dan ruang publik dipenuhi suara keras namun miskin hikmah. Buya Hamka menawarkan jalan lain yakni keberagamaan yang teduh, berilmu, dan beradab.
Aktualitas sejarah Buya Hamka dengan kondisi kini tampak jelas. Saat literasi melemah dan diskursus dangkal menguat, ia mengingatkan pentingnya membaca dan menulis sebagai ibadah intelektual.
Saat agama kerap direduksi menjadi simbol dan slogan, ia menegaskan bahwa inti agama adalah akhlak. Saat nasionalisme dipersempit, ia menunjukkan bahwa cinta tanah air tidak bertentangan dengan iman, karena sejatinya malah saling menguatkan. Buya Hamka berdiri sebagai jembatan antara iman dan kemanusiaan, antara tradisi dan modernitas.
Lalu, bagaimana merancang masa depan dengan nilai-nilai Buya Hamka? Pertama, membangun pendidikan yang memerdekakan akal dan menumbuhkan adab. Ilmu harus melahirkan kerendahan hati, bukan kesombongan.
Kedua, merawat ruang publik yang beretika. Perbedaan dirawat sebagai rahmat, bukan bahan permusuhan. Ketiga, meneguhkan peran intelektual dan ulama sebagai penjaga nurani bangsa, bukan sekadar komentator atau pendukung kekuasaan.
Keempat, menghidupkan budaya menulis dan berpikir panjang. Karena bangsa besar didasari dan dibangun oleh gagasan dan tindakan nyata yang konsisten.
Buya Hamka telah pergi, tetapi nilai-nilainya tinggal sebagai kompas. Ia mengajarkan bahwa hidup adalah pengabdian, ilmu adalah amanah, dan kekuasaan hanyalah ujian.
Dalam sunyi perpustakaan dan riuh sejarah, ia memilih jalan yang konsisten. Berpihak pada kebenaran, meski harus sendiri. Dari sana kita belajar merancang masa depan bukan dengan kemarahan, melainkan dengan kejernihan; bukan dengan kegaduhan, melainkan dengan kerja yang berakar pada nilai luhur.
Di zaman yang serba cepat ini, Buya Hamka mengajak kita melambat sejenak. Mendengar hati, menajamkan akal, dan menata langkah. Sebab masa depan yang beradab tidak lahir dari amarah, tetapi dari kesadaran.