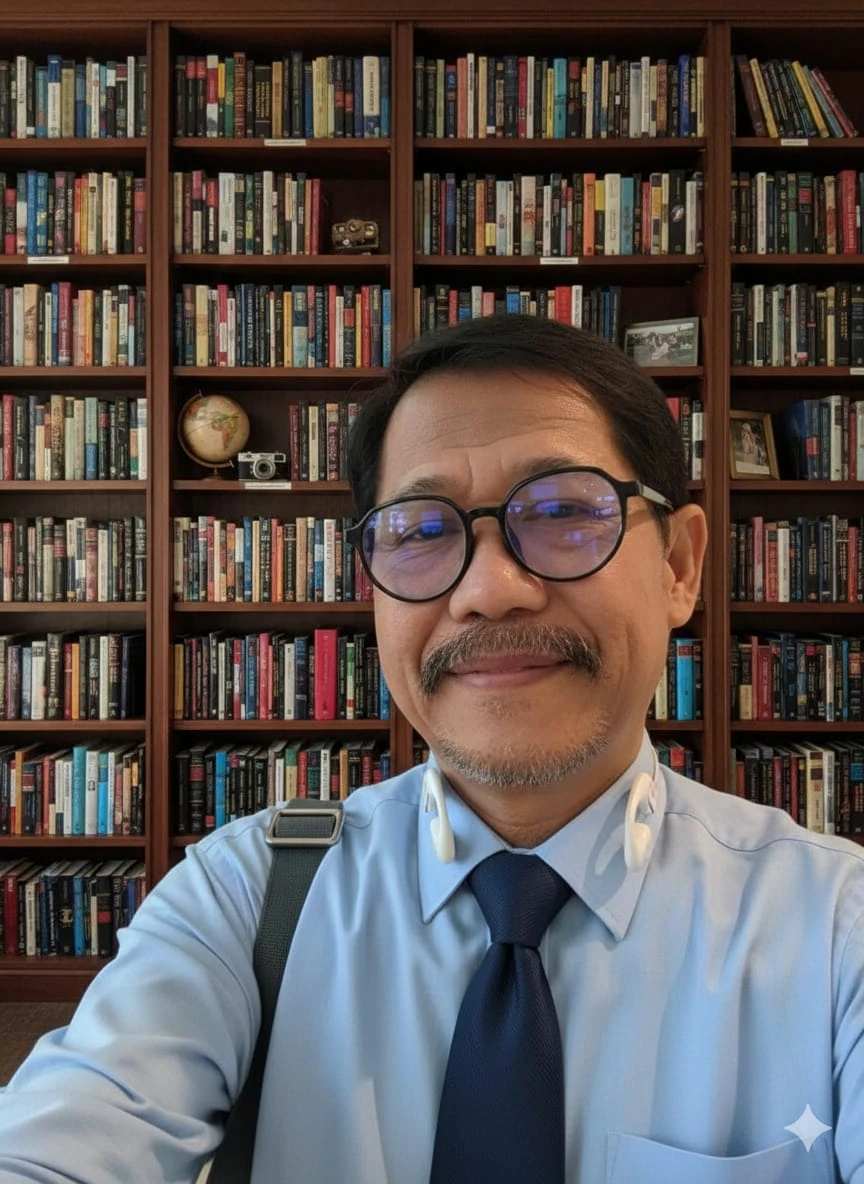Oleh: Muliadi Saleh*
Masyarakat Mandar mengenalnya sebagai seorang ulama karismatik, pejuang kemerdekaan, dan figur spiritual yang jejaknya tak lekang dimakan waktu. Namun bagi Indonesia hari ini, ia mewakili sesuatu yang jauh lebih luas: model leadership spiritual yang relevan bagi kehidupan modern yang penuh kegelisahan.
Dalam literatur kepemimpinan kontemporer, dikenal istilah spiritual leadership, yaitu kepemimpinan yang bertumpu pada makna, nilai, keteladanan, dan keterhubungan antara pemimpin dan komunitasnya.
Jika konsep ini ditarik ke lanskap Mandar abad ke-19, maka kita menemukan tubuh dan ruhnya bersatu dalam sosok KH. Muhammad Thahir Imam Lapeo.
Imam Lapeo lahir pada 1839 di Pambusuang, desa pesisir yang akrab dengan suara ombak dan disiplin agama. Dari ayahnya, seorang penghafal Al-Qur’an, ia mewarisi kekhusyukan membaca ayat; dari ibunya yang berdarah bangsawan, ia menyerap ketegaran dan kehormatan diri.
Sejak kecil, ia bukan hanya tekun mengaji, tetapi haus mencari pengetahuan. Al-Qur’an ia khatamkan berkali-kali, seakan ingin menyelami kedalaman makna yang tak pernah habis. Di usia remaja, ia menekuni bahasa Arab dan ilmu alat; langkah awal yang kelak membuka gerbangnya menuju dunia keilmuan Islam yang lebih luas.
Rihlah intelektualnya membentang dari Sulawesi hingga Sumatra, lalu mencapai pusat-pusat peradaban Islam pada masanya. Ia belajar di Parepare, menimba ilmu di Pulau Salemo, menyelami tradisi keilmuan di Padang, sebelum akhirnya berangkat ke Makkah.
Di Tanah Suci, ia bertemu para ulama besar, memperdalam fiqih, tafsir, tasawuf, dan ilmu kalam. Catatan sejarah lokal juga menyebut perjalanannya hingga Istanbul, menandai betapa luas horison intelektualnya.
Dari perjalanan itulah ia pulang sebagai seorang ulama matang—bukan hanya cerdas, tetapi juga bening jiwanya; bukan hanya alim, tetapi juga peka terhadap masalah kehidupan masyarakat.
Sekembalinya di Mandar, ia tidak memilih pusat kekuasaan atau kota yang hiruk pikuk. Ia justru menuju Lapeo, sebuah desa tenang di Campalagian. Di sanalah ia membangun Masjid Nurut Taubah, masjid yang menjadi jantung pendidikan Islam dan pusat transformasi sosial.
Dalam perspektif akademik, masjid itu bukan sekadar rumah ibadah, melainkan institusi kepemimpinan yang membentuk kesadaran kolektif. Di dalamnya, Imam Lapeo mengajarkan fiqih dan akhlak, membimbing para santri, menuntun masyarakat, dan menanamkan nilai yang hari ini kita sebut sebagai leadership based on spirituality—kepemimpinan yang bertumpu pada makna, keteladanan, dan kedalaman moral.
Ketamakan kekuasaan tidak pernah menyentuh dirinya. Ketegasan yang ia miliki tidak memisahkan, tetapi justru merangkul. Dalam masa pendudukan Jepang, ia dikenal sebagai sosok yang dihormati, bahkan ditakuti, karena ketenangan dan keberaniannya.
Di masa damai, ia menjadi tempat masyarakat bertanya dan bernaung. Kepemimpinan seperti ini dalam kajian modern sering dipahami sebagai perpaduan antara integritas, kecerdasan emosional, dan kemampuan memancarkan kepercayaan; suatu bentuk otoritas moral yang lebih kuat dari sekadar struktur jabatan.
Makamnya yang berada di kompleks masjid hingga hari ini tidak pernah sepi. Arus peziarah datang dari berbagai daerah di Indonesia, membawa doa, harap, atau sekadar ingin merasakan keteduhan spiritual yang seolah menetap di udara Lapeo.
Fenomena ini bukan hanya tradisi religius, tetapi juga menunjukkan bahwa masyarakat masih mencari figur pemimpin yang autentik—yang memimpin dengan hati, bukan retorika; yang mengajarkan kebenaran melalui perilaku, bukan melalui klaim.
Dalam perspektif kekinian, leadership spiritual ala Imam Lapeo menawarkan refleksi penting bagi Indonesia yang tengah menghadapi polarisasi sosial dan kekeringan moral. Ia mengingatkan bahwa pemimpin sejati bukanlah mereka yang bersuara paling keras, tetapi yang paling jernih hatinya.
Bahwa kekuatan sejati lahir dari kemampuan memahami manusia, bukan sekadar mengatur mereka. Dan bahwa pendidikan, keteladanan, serta keberanian moral tetap menjadi fondasi terpenting bagi peradaban.
Di tengah era yang dipenuhi kecemasan, figur Imam Lapeo hadir bukan sebagai romantisme masa lalu, tetapi sebagai inspirasi untuk membaca ulang masa kini. Ia menegaskan bahwa kepemimpinan yang utuh tidak pernah lahir dari ambisi, melainkan dari pengabdian.
Tidak tumbuh dari struktur, tetapi dari keikhlasan. Dan bahwa cahaya yang ditanam dengan ketulusan akan terus hidup—bahkan setelah tubuhnya kembali menyatu dengan tanah.
Imam Lapeo mungkin telah berpulang lebih dari seabad lalu. Namun leadership spiritualnya, yang menggabungkan ilmu, keberanian, empati, dan keteladanan, tetap bergema sebagai tuntunan yang relevan bagi Indonesia modern.
Dari pesisir Mandar, cahaya itu berangkat; dan hingga kini, ia masih tidak berhenti menerangi.
*Penulis adalah Esais Reflektif dan Direktur Eksekutif Lembaga SPASIAL