Oleh: Khusnul Yaqin*
Di tengah hiruk pikuk kapitalisme global yang menancap kuat di jantung Amerika Serikat, muncul sosok yang mengingatkan kita pada figur legendaris dari sejarah Islam: Abu Dzar al-Ghifari. Ia bukan seorang sufi yang hidup di padang pasir, bukan pula seorang ulama yang berdebat tentang tafsir, melainkan seorang politisi muda keturunan Muslim yang kini memimpin kota paling simbolik dari kekuatan kapitalisme dunia—New York. Namanya Zohran Mamdani.
Mamdani, lahir dari keluarga imigran Uganda–India, bukanlah tokoh politik biasa. Ia menapaki jalur politik dengan semangat sosialisme progresif yang menentang ketimpangan ekonomi dan kezaliman struktural yang selama ini dianggap wajar di sistem Amerika. Ketika ia terpilih menjadi wali kota Muslim pertama New York City, banyak yang terkejut: bagaimana mungkin kota yang menjadi ikon kebebasan, tetapi juga ketimpangan, kini dipimpin oleh seorang sosialis Muslim yang berani menantang kepentingan para miliarder?
Sejak hari pertama menjabat, Mamdani langsung menandai arah kepemimpinannya: menaikkan pajak bagi mereka yang berpenghasilan di atas satu juta dolar per tahun. Pajak ini bukan sekadar simbol, tetapi wujud nyata redistribusi kekayaan dalam sistem yang sudah terlalu lama berpihak kepada segelintir orang. Hasil pajak tersebut ia salurkan untuk kepentingan sosial—transportasi gratis, layanan penitipan anak universal, dan pembangunan perumahan terjangkau.
Langkah-langkah ini membuat kaum miliarder di New York gusar. John Catsimatidis, seorang pengusaha besar dan miliarder minyak, bahkan mengaku frustrasi dan menyebut kebijakan Mamdani sebagai “ancaman terhadap iklim bisnis.” Namun, bagi banyak warga New York kelas pekerja, Mamdani adalah sosok penyelamat yang menyalakan kembali harapan bahwa kota mereka bisa menjadi tempat yang manusiawi, bukan sekadar arena kompetisi tak berujung.
Kisah ini mengingatkan kita pada Abu Dzar al-Ghifari, sahabat Nabi Muhammad SAW yang dikenal karena keberaniannya mengkritik para penguasa dan orang kaya di masanya. Abu Dzar adalah suara hati nurani Islam, yang tak gentar menegur khalifah atau pejabat manapun ketika melihat ketimpangan. Ia terkenal dengan seruannya yang mengguncang para pemilik harta: “Apabila engkau menimbun kekayaan, maka engkau sedang menyalakan api neraka untuk dirimu sendiri.”
Mamdani, dalam konteks modern, tampak mewarisi semangat yang sama. Ia tidak mengangkat senjata atau berkhutbah dari mimbar, tetapi menyalurkan gagasan keadilan sosial melalui kebijakan publik. Dalam sistem demokrasi liberal Amerika yang sering kali dikuasai oleh lobi koboi korporasi dan uang besar, keberanian Mamdani untuk menentang status quo adalah bentuk jihad sosial yang langka.

Zohran Mamdani melambaikan tangan kepada para pendukungnya saat malam kemenangan pemilihan wali kota New York City. Di belakangnya terpampang tulisan besar “ZOHRAN for NEW YORK CITY” yang menjadi slogan kampanye progresifnya.Foto ini menangkap simbol perubahan: seorang “Abu Dzar dari New York” yang menyalakan kembali idealisme moral di tengah sistem sekuler Amerika.
Namun, seperti halnya Abu Dzar yang diasingkan karena keberaniannya, Mamdani pun menghadapi tekanan dan resistensi dari kaum elit New York. Media arus utama menuduhnya sebagai populis kiri yang tak paham ekonomi. Investor mengancam akan hengkang. Tapi Mamdani tidak mundur. Ia menyadari bahwa setiap revolusi sosial memerlukan keberanian moral, bukan sekadar kalkulasi politik.
Di mata sebagian orang, kebijakan Mamdani mungkin tampak ekstrem. Pajak tinggi bagi orang kaya? Toko kelontong milik pemerintah? Transportasi gratis untuk semua? Namun, jika kita menengok ke dalam nilai-nilai Islam, gagasan-gagasan ini justru sangat selaras dengan prinsip keadilan distributif yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Islam menolak penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an: “Agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya di antara kamu.” (QS. Al-Hasyr: 7).
Mamdani tidak berbicara dalam bahasa agama, tetapi tindakannya berbicara dalam bahasa moral universal yang diakui oleh Islam: menolong yang lemah, menegakkan keadilan, dan menolak keserakahan. Ia tidak sedang berdakwah secara lisan, tetapi kebijakan-kebijakannya adalah bentuk dakwah sosial yang nyata.
Namun, di tengah popularitasnya, banyak yang mencoba menyeret Mamdani ke medan isu internasional. Ada yang menuntutnya bersuara tentang kezaliman global, tentang Palestina, tentang imperialisme Barat. Padahal, tugasnya saat ini bukan menjadi diplomat dunia, melainkan pelayan masyarakat New York. Ia bukan pemimpin global, tetapi wali kota sebuah kota dengan 8 juta jiwa dan kompleksitas sosial luar biasa.
Menuntut Mamdani untuk memikul isu-isu global di pundaknya adalah kekeliruan yang mengalihkan fokus perjuangannya. Ia sedang mengurusi sistem kesejahteraan yang rapuh, memperjuangkan hak anak-anak pekerja imigran untuk mendapat pendidikan yang layak, dan memperluas akses layanan publik yang sudah lama dimonopoli swasta. Dalam konteks ini, tanggung jawabnya sangat lokal, tetapi dampaknya universal.
Abu Dzar pun dahulu tidak berbicara tentang urusan geopolitik, melainkan tentang kesenjangan sosial di Madinah. Ia menegur penguasa bukan karena kebijakan luar negeri, tetapi karena kemewahan yang tidak berpihak pada kaum miskin. Mamdani menapaki jalur serupa: membenahi moralitas ekonomi, bukan memperluas konflik politik.
Dalam kacamata etika Islam, apa yang dilakukan Mamdani adalah bentuk “amar makruf nahi munkar” dalam sistem modern. Ia menyeru kebaikan dalam bentuk redistribusi sumber daya, dan mencegah kemungkaran dalam bentuk monopoli kekayaan. Ketika ia membangun toko kelontong milik pemerintah agar harga bahan pokok menjadi terjangkau, ia sedang menolak bentuk baru dari penindasan kapitalistik—penindasan yang membuat orang miskin harus membayar lebih mahal hanya untuk hidup.
Apa yang membuat kisah Mamdani menarik bukan hanya karena ia Muslim, tetapi karena ia menghadirkan spiritualitas keadilan dalam sistem sekuler. Ia menunjukkan bahwa menjadi pemimpin Muslim di dunia Barat bukan berarti membawa simbol agama, tetapi membawa nilai-nilai profetik ke ruang publik: kejujuran, empati, dan keberpihakan kepada yang tertindas.
Kepemimpinan seperti ini penting di era ketika dunia mengalami keletihan moral. Banyak pemimpin Muslim yang gemar berbicara tentang solidaritas internasional, tetapi lupa menegakkan keadilan di lingkungan terdekatnya. Mamdani justru melakukan sebaliknya—ia tidak banyak bicara tentang dunia, tetapi bertindak nyata di komunitasnya. Ia memahami bahwa revolusi sosial dimulai dari kota, dari tetangga, dari layanan publik yang adil.
Dalam tradisi Islam, Rasul SAW bersabda: “Barang siapa tidak peduli terhadap urusan kaum Muslimin, maka ia bukan dari golongan mereka.” Mamdani mungkin tidak menggunakan istilah “kaum Muslimin” secara eksklusif, tetapi kepeduliannya terhadap kaum tertindas di New York sejatinya mencerminkan semangat hadis itu. Ia menjadikan kepemimpinan sebagai pelayanan, bukan alat kekuasaan.
Di tengah gelombang politik yang semakin ke kanan, kemunculan Mamdani adalah anomali yang menyegarkan. Ia membuktikan bahwa nilai-nilai sosialisme, jika dipraktikkan dengan hati nurani, bisa menjadi jembatan antara dunia modern dan etika profetik. Dalam dirinya, Abu Dzar menemukan duplikasi modern—seorang yang berbicara dengan tindakan, bukan slogan; yang melawan dengan kebijakan, bukan kemarahan.
Mungkin sebagian orang akan menuduh perbandingan ini berlebihan. Abu Dzar hidup di padang pasir Arabia abad ke-7, sementara Mamdani hidup di kota metropolitan abad ke-21. Namun, semangat keduanya sama: menolak ketidakadilan yang dilegalkan oleh sistem. Di dunia yang semakin terfragmentasi oleh politik identitas, Mamdani memilih jalan moralitas: jalan keadilan sosial.
Ia bukan sosok sempurna. Tidak semua kebijakannya akan berhasil. Akan ada kompromi, penolakan, bahkan mungkin kegagalan. Tapi sejarah selalu berpihak pada mereka yang berani menyalakan api moralitas di tengah kegelapan sistem. Seperti Abu Dzar yang hidup miskin tetapi dikenang kaya oleh sejarah, Mamdani pun mungkin akan meninggalkan warisan yang jauh lebih besar dari sekadar jabatan wali kota. Ia akan dikenang sebagai simbol bahwa keadilan sosial bisa tumbuh bahkan di jantung kapitalisme global.
Mamdani bukanlah Nabi, bukan pula Imam. Tapi ia adalah pengingat bahwa nilai-nilai kenabian bisa hidup kembali di tengah sistem yang sekuler, bahwa iman sosial tidak mengenal batas agama atau geografi. Dari New York, ia menghidupkan kembali pesan abadi Islam: bahwa kekuasaan sejati bukanlah menguasai orang lain, melainkan melayani mereka yang tertindas.
Mungkin, jika Abu Dzar hidup hari ini, ia akan tersenyum melihat pemuda Muslim, pengikut Ali itu berdiri di balai kota New York, mengumumkan pajak untuk para miliarder, dan berkata dengan lantang: “Keadilan bukan milik langit, ia harus ditegakkan di bumi.”
*Penulis adalah Guru Besar pada Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin
 Prof.Dr.Ir.Khusnul Yaqin,M.Sc., seorang pakar dalam bidang ekotoksikologi perairan, ia juga dikenal sebagai penulis dan pengamat sosial yang menyoroti isu keadilan, kemanusiaan, dan moralitas publik. Artikel “Mamdani, Abu Dzar dari New York” merupakan refleksi etisnya tentang kepemimpinan berkeadilan dalam dunia modern.
Prof.Dr.Ir.Khusnul Yaqin,M.Sc., seorang pakar dalam bidang ekotoksikologi perairan, ia juga dikenal sebagai penulis dan pengamat sosial yang menyoroti isu keadilan, kemanusiaan, dan moralitas publik. Artikel “Mamdani, Abu Dzar dari New York” merupakan refleksi etisnya tentang kepemimpinan berkeadilan dalam dunia modern.


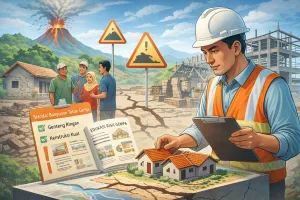
-300x200.webp)







