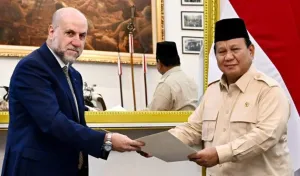Oleh: Khusnul Yaqin*
Sampah plastik telah menjadi simbol kegagalan peradaban modern dalam menyeimbangkan kenyamanan hidup dengan keberlanjutan lingkungan. Kita menyaksikan sendiri bagaimana plastik-plastik sekali pakai berserakan di sungai, tertimbun di TPA, dan lebih tragis lagi—terurai menjadi mikro dan nanoplastik di laut, sungai, tanah, bahkan tubuh manusia. Dunia kini tidak hanya menghadapi darurat iklim, tapi juga darurat plastik.
Dampaknya menyebar ke mana-mana. Plastik mencemari estetika lingkungan, membunuh biota akuatik dan darat, mengganggu rantai makanan, dan telah masuk ke jaringan tubuh manusia. Ilmuwan telah menemukan mikroplastik di darah, paru-paru, bahkan plasenta manusia. Konstelasi ekosistem kita, yang sejatinya merupakan penopang kehidupan, kini seperti jaring laba-laba yang mulai koyak oleh jejak antropogenik yang sembrono.
Kita tidak bisa lagi bersikap seolah-olah plastik hanya masalah kebersihan. Plastik adalah masalah politik, ekonomi, teknologi, bahkan spiritual. Mengelola plastik bukan sekadar mengumpulkan dan mendaur ulang, melainkan mereformulasi hubungan manusia dengan limbahnya sendiri. Pendekatan permukaan seperti menjadikan sampah plastik sebagai ekobrik, kerajinan tangan, atap rumah, atau campuran beton jalan memang terlihat baik. Namun, itu hanya menunda datangnya bencana. Cepat atau lambat, ekobrik itu akan lapuk, kerajinan itu akan rusak, atap itu akan berganti, dan semua akan kembali menjadi sampah plastik—bahkan dalam bentuk mikro yang lebih berbahaya.
Kita butuh solusi yang tidak hanya menahan limbah, tetapi mengakhirinya. Salah satu jalan yang kini mulai dilirik adalah mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar melalui teknologi pirolisis. Dengan proses pemanasan tertutup tanpa oksigen, plastik dapat dikonversi menjadi bahan bakar cair seperti diesel atau bensin sintetis. Ini bukan hanya menjawab krisis plastik, tetapi juga membuka peluang energi alternatif dari limbah yang sebelumnya dianggap tak berguna.
Namun, teknologi saja tidak cukup. Tanpa sistem pengelolaan dan edukasi yang menyertainya, pirolisis pun akan gagal seperti pendekatan sebelumnya. Di sinilah kampus sebagai simpul intelektual dan sosial dapat mengambil peran besar. Universitas tidak boleh hanya menjadi menara gading yang pasif terhadap krisis ekologi. Sebaliknya, kampus harus menjadi laboratorium sosial yang mengintegrasikan inovasi, edukasi, dan aksi konkret.
Salah satu langkah nyata yang bisa dilakukan adalah mendirikan bank sampah plastik di setiap fakultas, atau bahkan setiap unit kegiatan mahasiswa. Bank sampah ini bukan sekadar tempat mengumpulkan plastik, tapi menjadi pusat edukasi, penelitian, dan transformasi nilai limbah menjadi energi. Dengan menggandeng alat pirolisis skala kecil hingga menengah, plastik yang terkumpul bisa segera diubah menjadi bahan bakar yang bisa digunakan untuk keperluan rumah tangga, kendaraan operasional kampus, atau bahkan cadangan energi untuk bencana.
Keterlibatan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan akan menciptakan ekosistem kesadaran baru: bahwa plastik bukan hanya masalah orang lain, tapi tanggung jawab bersama. Plastik dari botol minuman di kantin, kemasan makanan praktis, atau tas kresek di koper mahasiswa tidak lagi dibuang sembarangan, tapi menjadi titik tolak untuk produksi energi ramah lingkungan.
Dalam jangka panjang, program bank sampah dan pirolisis ini tidak hanya mengurangi beban TPA, tapi juga membangun ekonomi sirkular. Nilai ekonomi muncul karena bahan bakar hasil pirolisis bisa dikomersialisasikan secara terbatas di sektor informal, atau digunakan langsung oleh komunitas. Di sisi lain, nilai ekologisnya terletak pada pencegahan pencemaran lebih lanjut, pengurangan emisi karbon, dan kontribusi nyata terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Sampah plastik sekali pakai mencemari lingkungan dan membahayakan makhluk hidup. Sudah saatnya kita bertindak! Kurangi, gunakan kembali, daur ulang, dan utamanya: STOP penggunaan plastik sekali pakai. Tanggung jawab kita bersama untuk lingkungan yang lebih bersih. Kredit: x.com.
Agar program ini efektif, perlu kemitraan antara universitas, pemerintah daerah, dan sektor swasta. Pemerintah dapat menyediakan insentif bagi kampus yang berhasil mengolah limbah plastiknya sendiri. Sektor industri dapat mendukung dengan menyediakan teknologi pirolisis yang efisien dan ramah lingkungan. Sementara itu, kampus menjadi motor edukasi dan inovasi, tempat di mana teori bertemu praktik, dan solusi lahir dari kebutuhan nyata.
Di beberapa negara maju, pendekatan seperti ini mulai dikembangkan. Namun di Indonesia, dengan jumlah penduduk mahasiswa yang sangat besar dan ragam aktivitas akademik yang tinggi, potensi dampaknya jauh lebih besar. Bayangkan jika setiap universitas negeri dan swasta memiliki sistem bank sampah dan unit pirolisis terintegrasi. Plastik dari aktivitas kampus, masyarakat sekitar, hingga mitra industri bisa masuk ke sistem ini dan menghasilkan bahan bakar yang membantu kampus mandiri energi. Sebuah lompatan dari masalah menjadi solusi.
Tentu ada tantangan. Biaya awal investasi alat pirolisis, pelatihan SDM, pengawasan kualitas bahan bakar, dan risiko emisi harus ditangani dengan bijak dan ilmiah. Tetapi risiko stagnasi dan kerusakan lingkungan jauh lebih berbahaya bila kita memilih diam. Lebih baik kita gagal karena mencoba, daripada menjadi generasi yang disalahkan karena abai.
Lebih dari itu, mengelola plastik dengan pendekatan transformasional seperti ini juga memberi pesan moral: bahwa manusia bertanggung jawab terhadap ciptaan Tuhan. Dalam banyak tradisi spiritual, limbah dipandang sebagai bagian dari ketidakseimbangan hidup. Maka upaya membersihkan dan mengelola limbah adalah bagian dari pensucian ruang hidup dan kesadaran diri.
Kampus sebagai pusat ilmu dan teknologi tidak bisa sekadar menjadi pengamat. Kampus harus menjadi pionir perubahan. Revolusi pengelolaan plastik harus dimulai dari kelas-kelas, laboratorium, ruang dosen, kantin mahasiswa, hingga titik-titik bank sampah fakultatif. Dari sana, lahirlah perubahan perilaku dan sistem yang mengakar.
Jika kita tidak segera bertindak, lautan akan semakin penuh dengan serpihan plastik, tanah akan jenuh oleh partikel mikro, dan udara akan kotor oleh emisi tak terlihat. Tapi jika kita berani mengubah paradigma—dari plastik sebagai masalah menjadi plastik sebagai sumber energi—maka kita tidak hanya menyelamatkan lingkungan, tapi juga membuka jalan menuju masa depan yang mandiri secara energi, bersih secara ekologis, dan adil secara sosial.
Inilah saatnya mengubah plastik menjadi api harapan, bukan bara kehancuran.
*Penulis adalah Guru Besar Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin

-300x225.webp)