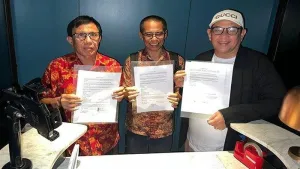Di dalam kuasa negara, ada lapisan-lapisan kepentingan yang menahun, seperti akar-akar tua yang saling membelit. Ada birokrasi yang lebih tua dari usia para menteri, yang berjalan dengan logika sendiri, lambat namun keras kepala, seperti mesin besar yang tak mudah digerakkan.
Ada politik yang selalu mencari celah: lobi-lobi di ruang gelap, janji-janji yang berganti arah sesuai angin, dan kesepakatan yang kerap lebih menentukan dibanding visi.
Di situlah idealisme diuji. Ia bisa bertahan, tapi sering kali ia harus berkompromi. Dan setiap kompromi, betapapun kecilnya, adalah retakan. Satu retakan membuka jalan bagi retakan lain.
Hingga akhirnya, semangat yang dulu dibawa dengan keyakinan penuh, perlahan kehilangan bentuknya. Apa yang awalnya adalah janji perubahan, bisa berubah menjadi sekadar proyek, dan kadang, proyek itu hanyalah nama lain dari kebiasaan lama yang dilanggengkan.
Nietzsche pernah menulis: “He who fights with monsters should look to it that he himself does not become a monster.” Barang siapa melawan monster, jangan sampai ia sendiri berubah menjadi monster.
Kata-kata itu terdengar seperti gema yang ironis. Sebab dalam sistem yang korup, idealisme bisa pelan-pelan meniru wajah lawannya. Apakah Nadiem melakukan kesalahan prosedur?
Sejarah Indonesia menyimpan banyak jejak orang muda yang masuk ke pemerintahan dengan janji segar, hanya untuk keluar dengan beban luka. Mereka datang dengan keyakinan bahwa usia muda membawa keberanian untuk melawan kebiasaan lama, bahwa ide-ide baru bisa mengalahkan kelumpuhan birokrasi.
Namun, yang mereka temui sering kali adalah tembok yang tak mudah ditembus: jaringan patronase yang telah lama berakar, kompromi politik yang menuntut kesetiaan pada kepentingan, bukan pada gagasan.
Ada yang bertahan sebentar, lalu menyerah; ada yang mencoba mengubah dari dalam, namun perlahan kehilangan bentuk asli dirinya.
Mereka yang dahulu dielu-elukan sebagai simbol harapan, sering pulang dengan wajah letih, kadang dengan reputasi yang tercemar, kadang dengan idealisme yang terkikis, dan kadang dengan kesadaran pahit bahwa mereka telah menjadi bagian dari lingkaran yang dulu mereka lawan.
Hannah Arendt suatu ketika mengingatkan: “The sad truth is that most evil is done by people who never make up their minds to be good or evil.” Kebenaran yang menyedihkan adalah bahwa sebagian besar kejahatan lahir bukan dari niat jahat besar, melainkan dari ketidakmampuan memilih untuk tetap setia pada kebaikan.
Di akhir cerita, kita mungkin harus mengakui: perjalanan menjaga idealisme lebih berat daripada mendirikan Gojek. Dan di situlah tragedi Nadiem, ia bukan hanya tentang seorang individu, tetapi tentang betapa rapuhnya harapan ketika bertemu realitas kuasa.
*Penulis adalah blogger, peneliti, dan digital strategist. Lulus kuliah di Unhas, UI, dan Ohio University. Kini tinggal di Bogor, Jawa Barat