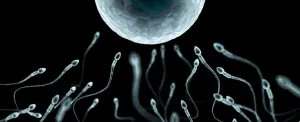UNHAS.TV - Pada Jumat (29/8/2025) malam, langit Kota Makassar memerah bukan karena senja. Api menjilati gedung DPRD kota Makassar. Pun gedung DPRD Sulsel. Puluhan kamera ponsel menyala.
Dalam hitungan detik, video rekaman ponsel itu berpindah tangan, dari satu gawai ke gawai lain, melintasi ruang, waktu, dan batas negara.
Sepekan kemudian, di sisi bumi lain, di Kathmandu, Nepal, ribuan anak muda menyalakan layar ponsel mereka untuk alasan yang sama, melakukan protes.
Dua kota, dua negara, dua konteks berbeda, namun berdenyut dalam satu irama digital. Inilah wajah baru perlawanan, sebuah gerakan sosial yang diambil alih oleh media sosial.
“Kalau dulu mau menyampaikan aspirasi, kita harus datang ke DPR. Sekarang cukup lewat handphone,” ujar pakar komunikasi politik dari Universitas Hasanuddin, Dr Hasrullah MA, dalam program Unhas Speak Up.
Lebih lanjut, Hasrullah berbicara di hadapan kamera dengan suara yang sarat peringatan. “Ini revolusi komunikasi dan kita sedang hidup di tengah-tengahnya,” lanjutnya.
Hasrullah menggambarkan perubahan besar yang terjadi dalam dua dekade terakhir. Di abad ke-20, “media maya” masih terbatas pada internet sederhana.
Belum ada YouTube, tak ada Instagram, belum ada TikTok, apalagi Discord yang kini bisa melahirkan perdana menteri dadakan seperti di Nepal. Tapi dalam waktu singkat, media sosial mengambil alih ruang publik, bahkan ruang privat manusia.
Hasrullah mengutip Doris Graber dalam The Power of Media, yang menyebut dua hal penentu utama dalam ledakan pengaruh digital yakni filter bubble dan algoritma. Dua mesin tak kasat mata yang mengatur apa yang kita lihat, rasakan, bahkan pikirkan.
“Kita disaring, diarahkan, dan digiring,” katanya. “Kadang tanpa sadar, kita bukan lagi pencari informasi, tapi kita yang dicari oleh informasi.”
Nepal: Dari Game ke Parlemen Digital
Kisah di Nepal menjadi contoh ekstrem betapa kuatnya pengaruh media sosial ini. Awalnya, Discord hanya digunakan oleh para gamer, yakni ruang tempat anak muda bercanda di sela permainan daring.
Tapi saat pemerintahan dianggap tak bersih, para pengguna mulai membuka kanal-kanal diskusi politik. Mereka berdebat, berorasi, hingga suatu hari membentuk “parlemen digital” yang menelurkan sosok perdana menteri sementara.
Semua bermula dari rasa muak terhadap korupsi dan hedonisme elite. “Sama seperti yang kita lihat di sini (Indonesia),” ujar Hasrullah.
“Ketika realitas yang terjadi di dunia nyata selaras dengan narasi di media sosial, maka gerakan itu meledak. Tidak ada sensor, tidak ada penyangga, dan ia tumbuh otomatis, automatically, kata orang sana.”
Algoritma bekerja seperti aliran magma di bawah permukaan tanah—senyap, tapi mematangkan ledakan. Dari sana, simbol-simbol perlawanan menyebar. Hashtag jadi panji, meme jadi manifesto.
Makassar: Nyala Api di Tengah Layar
Lantas, apa yang terjadi di Makassar, menurut Hasrullah, adalah bentuk paling nyata dari teori itu. Ketika video protes dan pembakaran di Jakarta beredar, dalam hitungan menit, emosi yang sama menjalar hingga Sulawesi.
“Saya sempat di lokasi,” ujarnya mengenang. “Awalnya aman. Tapi 10–20 menit kemudian, suasana berubah. Saya lihat langsung bagaimana massa bergerak, dan api mulai menyala.”
Fenomena itu, katanya, bukanlah kebetulan. Ia hasil dari keterhubungan digital yang melampaui ruang fisik. Di dalam filter bubble media sosial, setiap unggahan, komentar, dan potongan video memperkuat keyakinan yang sama, bahwa kemarahan mereka sah.
“Itu teori peluru panas dalam komunikasi. Begitu pesan ditembakkan, dan mengandung kebenaran yang dirasakan massa, tidak ada yang bisa menghentikannya,” jelas Hasrullah.
Homofili dan Narasi Milenial
>> Baca Selanjutnya undefined
undefined