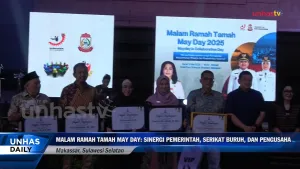Pagi itu, langit Chicago kelabu. Tanggal 1 Mei 1886, ribuan buruh berbaris di jalanan membawa satu tuntutan: delapan jam kerja sehari. Mereka datang dari pabrik, pelabuhan, hingga kantor-kantor kecil yang menjamur di tengah kota yang tumbuh karena Revolusi Industri.
Tuntutan mereka terdengar sederhana bagi telinga kita hari ini. Tapi di masa itu, mereka dianggap pemberontak.
Empat hari setelah demonstrasi itu, di Haymarket Square, sebuah ledakan mengguncang kerumunan. Polisi membalas dengan tembakan. Delapan polisi tewas, puluhan buruh juga jatuh.
Dalam keributan dan kekacauan, hukum dijalankan seperti sumbu api: cepat, panas, dan membakar keadilan. Delapan aktivis buruh ditangkap, empat di antaranya digantung. Mereka tak pernah terbukti melempar bom.
Tapi kematian mereka tak sia-sia. Justru dari tragedi itulah lahir May Day, Hari Buruh Internasional, yang kini dirayakan di lebih dari 80 negara.
***
Di Indonesia, jejak perayaan Hari Buruh berawal dari zaman kolonial. Tahun 1920 menjadi momen pertama kalinya 1 Mei dirayakan di Hindia Belanda oleh serikat-serikat buruh yang dipengaruhi gerakan kiri seperti Sarekat Rakyat.
Di tengah kebangkitan kesadaran politik bumiputera, para buruh mulai menyuarakan hak mereka: upah layak, waktu kerja terbatas, dan jaminan hidup. Kolonialisme, bagi mereka, bukan sekadar soal perampasan tanah, tapi juga tenaga.
Namun perayaan itu tak berlangsung lama. Pemerintah Hindia Belanda mencurigai May Day sebagai gerakan revolusioner. Setelah pemberontakan komunis 1926, semua bentuk peringatan dilarang.
Setelah Indonesia merdeka, Presiden Sukarno menghidupkan kembali peringatan 1 Mei sebagai simbol solidaritas buruh internasional. Dalam semangat anti-imperialisme dan revolusi, buruh dianggap garda depan pembangunan.
Di era ini, bendera merah dan orasi keras bukan hal tabu. Demonstrasi buruh adalah bagian dari wajah republik yang muda dan masih mencari bentuk.
Namun, semua berubah saat Orde Baru berkuasa.
Soeharto melihat pergerakan buruh sebagai ancaman stabilitas. Organisasi buruh direduksi menjadi perpanjangan tangan negara: SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) dibentuk dan dipasung. May Day tak boleh dirayakan. Buruh dilarang turun ke jalan. Semua aspirasi disalurkan lewat forum-forum internal yang dikontrol penguasa.
Selama tiga dekade lebih, 1 Mei sunyi. Buruh bekerja seperti biasa, dan kalender tak menandainya dengan warna merah. Tapi diam bukan berarti padam.
***
Tahun 1998 menjadi titik balik. Reformasi membuka keran demokrasi. Serikat-serikat buruh independen lahir kembali. Tuntutan lama kembali menggema: upah layak, penghapusan sistem kerja kontrak, hingga jaminan sosial.
Seiring waktu, 1 Mei kembali dirayakan di berbagai kota: Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar.
Puncaknya terjadi pada 2013, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan 1 Mei sebagai hari libur nasional. Keputusan itu adalah buah dari puluhan tahun perjuangan buruh, dari yang diam-diam bergerak hingga berani menembus barikade.
Hari ini, May Day di Indonesia lebih dari sekadar pawai. Ia adalah ruang simbolik tempat buruh menunjukkan eksistensinya—meski kerap dicibir. Di Jakarta, stadion Gelora Bung Karno kerap dipenuhi ribuan buruh dari pabrik-pabrik di pinggiran kota. Di Makassar, dari arah Biringkanaya hingga Pelabuhan Paotere, para buruh berkumpul dan melangkah bersama.
Mereka membawa poster: “Hapus Outsourcing!”, “Naikkan UMK!”, “Stop Union Busting!”. Tapi yang dibawa sebenarnya lebih dari itu: amarah yang diwariskan dari Haymarket, dari 1920, dari tahun-tahun sunyi Orde Baru, dan dari pabrik-pabrik tempat mesin tak pernah mati.
Hari ini, jika Anda menikmati delapan jam kerja, jika Anda punya hak cuti, jika Anda dilindungi dari pemecatan sewenang-wenang, maka ingatlah bahwa semua itu diperjuangkan. Tidak datang begitu saja. Dan May Day, lebih dari sekadar hari libur, adalah ingatan kolektif bahwa manusia bekerja bukan sebagai mesin.
Karena seperti yang pernah ditulis seorang aktivis buruh di awal abad ke-20: “Kami bukan roda gigi, kami manusia.”





-300x181.webp)