
Tiga rumah sakit lainnya dievakuasi karena tak aman lagi. Rumah Sakit Farabi di Kermanshah? Tinggal puing—langit-langit roboh, kaca berserakan. Pasien kanker kehilangan kemoterapi, dokter kehabisan alat, listrik padam—selamat datang di neraka.
Di Israel, Soroka Medical Center di Beersheba, yang melayani jutaan orang, hancur parah ketika rudal Iran mendarat pada 19 Juni 2025. Pasien dievakuasi, tapi rumah sakit hanya bisa menerima kasus darurat. Pasien lain? “Cari tempat sendiri, ya. Dan semoga beruntung!”
Akhirnya, rekonstruksi infrastruktur kesehatan jadi kebutuhan mendesak. Tanpa rumah sakit, korban luka tak terurus, penyakit kronis dibiarkan membusuk, dan sistem kesehatan masyarakat bisa rata dengan tanah. Ini bukan hanya soal tumpukan batu bata berselimut semen, tapi tentang nyawa yang bergantung pada dinding-dinding yang kini berserakan.
Di dalam Tubuh yang Sakit, Ada Jiwa yang Tersiksa
Perang tak cuma menyerang fisik, tapi juga mental dan emosional. Di Israel, hotline psikologis sampai kewalahan. Ada 4.700 panggilan masuk—naik 3.505%. Orang melapor panik, gemetar, takut buka pintu.
Anak-anak paling terdampak: seorang gadis di Tel Aviv berhenti bicara sejak serangan, seorang veteran perang PTSD-nya kambuh parah. Trauma psikologis akibat perang ini seperti bom waktu—bisa membuat generasi mendatang hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Lucu, ya? Meski dentuman senjata berhenti, gaung “ledakan” di kepala terus bergema sampai lama.
Di Iran, kerusakan lebih luas. Serangan ke fasilitas air dan sanitasi di utara membuat limbah (grey dan black) mencemari air bersih—selamat datang kolera dan diare.
Apalagi bagi anak-anak dan kelompok rentan yang sudah lapar dan terbatas aksesnya. Di Israel, 9.000 pengungsi berdesakan di penampungan darurat—surga bagi wabah menyebar. Sistem kesehatan jadi kacau. Bayangkan: meski selamat dari hujan rudal, tapi jadi korban karena diare. Ironi yang kejam, bukan?
Jalan Panjang, Berkelok, atau Buntu (?)
Perang Iran–Israel mengungkap wajah buruk sebuah konflik: bangunan sistem kesehatan hancur dan butuh puluhan tahun untuk dibangun kembali. Langkah nyata harus segera diambil.
Mari kita jujur: perang itu seperti novel murahan karena teknik penulisan yang buruk. Iran dan Israel bak dua anak TK yang rebutan mainan—tapi yang hancur bukan cuma mainan, melainkan sekalian dengan TK dan para staf pengajarnya.
Negara-negara yang bertikai seharusnya meletakkan kesehatan masyarakat di depan, bukan cuma jadi pelengkap pencapaian damai. Pelajaran dari sini? Mungkin saatnya kita sadar: harga perang bukan cuma uang atau tanah, tapi tentang jiwa yang tercabik dan harapan yang dikubur hidup-hidup.
Kalau tak berubah, ya, selamat menonton episode berikutnya dari kekacauan ini.
*Penulis adalah alumni Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Sejak tahun 2004, aktif dalam program kesehatan masyarakat dan pernah bertugas dari Aceh hingga Papua. Ia juga menulis, terutama di bidang sosial, budaya, filsafat, dan sastra. Ia bisa dihubungi melalui surel: darimakassar@gmail.com.

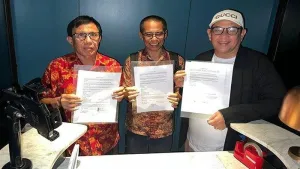
-300x210.webp)




-300x169.webp)



