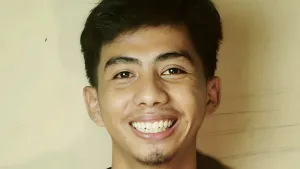Oleh: Khusnul Yaqin*
Di Surah Yasin, Al-Qur’an memilih kata yang sangat memukau untuk menggambarkan gerak kosmik. Ia tidak mengatakan bahwa matahari dan bulan “berlari”, tidak pula “berputar” secara mekanik seperti roda mesin. Al-Qur’an menggunakan kata yang lebih hidup, lebih organik, dan lebih bermakna: berenang. Kata itu adalah yasbahūn. Dengan satu kata ini, Al-Qur’an mengangkat gerak alam semesta dari sekadar fenomena fisika menjadi peristiwa ontologis. Alam tidak hanya bergerak, tetapi seakan bertasbih melalui keteraturan geraknya.
Ayatnya berbunyi:
لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ
Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya.
Kata yasbahūn berasal dari akar kata yang sama dengan tasbih. Dalam bahasa Arab klasik, sabaha berarti bergerak dengan ringan, mengalir, teratur, dan seimbang di dalam medium yang menopangnya. Ia tidak jatuh, tidak saling bertabrakan, dan tidak bergerak liar. Ketika Al-Qur’an menyebut benda-benda langit yasbahūn atau “berenang”, ia sedang menggambarkan ketaatan ontologis kosmos. Setiap makhluk berada dalam falak-nya, orbit eksistensialnya, tanpa melampaui batas dan tanpa menyerobot peran makhluk lain. Pada titik ini, tasbih tidak lagi sekadar ucapan lisan, tetapi menjadi gerak menuju keteraturan dan kesempurnaan wujud.
Jika kita meminjam bahasa kontemporer, yasbahūn dapat dibaca sebagai gerak kosmik yang terus-menerus mengikis entropi. Entropi di sini bukan sekadar konsep fisika, melainkan juga entropi moral dan eksistensial: kecenderungan menuju kekacauan, dominasi, dan perusakan. Alam, melalui yasbahūn-nya, terus bergerak ke arah keteraturan. Maka problem ekologis manusia modern bukan karena alam tidak teratur, melainkan karena manusia keluar dari falak-nya sendiri. Manusia menebang hutan secara serampangan, sehingga menyebabkan banjir air dan hanyutan kayu gelondongan.
Di sinilah Surah al-Hajj ayat 5, sebagaimana ditafsirkan Allamah Thabathabai dalam Tafsir al-Mīzān, menjadi jembatan konseptual yang sangat penting. Ayat ini menjelaskan bahwa wujud bersifat bertahap, bergerak, dan bermakna. Manusia tidak diciptakan sekaligus, tetapi melalui proses menjadi: dari tanah, setetes air, segumpal darah, segumpal daging, hingga lahir, tumbuh, dewasa, menua, dan kembali rapuh. Thabathabai menegaskan bahwa ayat ini bukan semata pelajaran biologi, melainkan pelajaran ontologi. Wujud tidak statis; ia bergerak dari potensi menuju aktual, dari kekurangan menuju kesempurnaan.
Jika prinsip ini diterapkan pada alam semesta, maka ekologi tidak dapat dipahami semata sebagai relasi material antarkomponen ekosistem sebagaimana dirumuskan oleh Odum, Haeckel, Warming, Clements, Cowles, dan Hutchinson. Tradisi empiris ini sangat berjasa karena memberi peta dan alat analisis yang presisi. Namun, peta—betapapun canggihnya—tetaplah peta. Ia tidak selalu berbicara tentang intensi ontologis dari wilayah yang dipetakan. Ekologi transenden mengajukan pertanyaan yang lebih dalam: apakah alam hanya sistem material yang dikelola, ataukah ia rangkaian wujud yang sedang menempuh perjalanan menuju kesempurnaan?
Dalam kerangka filsafat Islam, terutama melalui konsep ḥarakah al-jawhariyyah Mulla Sadra, seluruh alam berada dalam gerak substansial. Materi bukan titik akhir, melainkan tahap terendah dari wujud yang terus bergerak naik. Dengan taḥqīq al-wujūd, alam dipahami sebagai realitas bertingkat yang memancar melalui proses emanasi dari Wājib al-Wujūd hingga ke alam materi. Alam bukan benda mati yang netral, melainkan wujud yang memiliki arah, tujuan, dan adab.
Jika alam adalah wujud emanatif, maka pengelolaannya bukan sekadar persoalan teknis, melainkan persoalan amanah ontologis. Pertanyaannya kemudian: amanah itu berpijak pada apa? Dalam tradisi Islam, jawabannya jelas: insān kāmil. Insān kāmil adalah poros orientasi, wujud yang paling sadar terhadap struktur realitas, sehingga darinya lahir keseimbangan. Tanpa bimbingan insān kāmil, manusia mudah tergelincir menjadi pengelola yang arogan, meskipun membawa jargon keberlanjutan dan konservasi.

Ilustrasi kosmik Surah Yasin yang menggambarkan tasbih alam semesta—harmoni gerak langit, bumi, dan manusia sebagai pesan ekologis tentang keteraturan, keseimbangan, dan amanah menjaga ciptaan Tuhan.
Di sinilah relevansi hadis al-Thaqalayn menjadi sangat penting. Dalam riwayat yang tercatat dalam Ṣaḥīḥ Muslim, Nabi menyampaikan bahwa beliau meninggalkan dua perkara yang berat: Kitab Allah dan Ahlul Bait Nabi saw. Pesan ini sering dibaca sebagai wasiat keagamaan, tetapi dalam perspektif ekologi transenden, ia adalah pesan peradaban. Kitab Allah memberi peta kosmik, Ahlul Bait memberi teladan hidup. Tanpa keduanya, manusia kehilangan kompas. Ia mungkin cerdas secara teknis, tetapi buta arah secara eksistensial.
Kisah yang memberi bentuk emosional dan spiritual pada gagasan ini adalah hadis al-Kisā’. Ketika Nabi menghimpun Ali, Fatimah, Hasan, dan Husain di bawah kain, beliau tidak sekadar mendefinisikan keluarga biologis, tetapi menegaskan poros kesucian. Kata yasbahūn, sebagaimana disinggung dalam tradisi hadis al-Kisā’, berkaitan dengan cinta kepada mereka yang disucikan. Tanpa cinta kepada poros kesucian, tidak mungkin alam semesta bergerak dalam harmoni.
Tradisi ini berkaitan erat dengan Ayat al-Taṭhīr yang menegaskan pemurnian Ahlul Bait. Secara sosial, kisah ini mengajarkan bahwa kesucian bukan slogan, melainkan pusat gravitasi etika. Secara ekologis-transenden, ia memberi pesan bahwa poros teladan bukan berada di pinggir sejarah, tetapi di pusatnya. Ketika manusia terputus dari poros ini, relasi dengan alam menjadi rusak. Ketika manusia tersambung, relasi itu kembali tertata.
Pada titik ini, teori transpersonal ecology Warwick Fox menjadi dialog yang sangat menarik. Fox mengkritik ekologi yang masih berpusat pada ego sempit manusia. Ia mengusulkan transformasi menuju rasa diri yang meluas, di mana manusia tidak lagi memandang alam sebagai “yang lain”, tetapi sebagai bagian dari identitasnya. Dari transformasi ini lahir kepedulian ekologis yang lebih mendalam. Manusia menjaga alam bukan karena aturan, tetapi karena kesadaran bahwa melukai alam berarti melukai diri sendiri.
Namun, ekologi transenden melangkah lebih jauh dari sekadar perluasan identitas. Ia menegaskan bahwa transformasi harus memiliki arah. Perluasan diri tanpa poros berisiko menjadi kabur dan relativistik. Karena itu, cinta menjadi kunci—bukan cinta sentimental, tetapi cinta yang memurnikan orientasi. Di sinilah makna shalawat menemukan kedalaman ontologisnya. Allah sendiri berfirman:
إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
Shalawat bukan sekadar ucapan lisan. Ia adalah latihan penyambungan batin kepada poros wujud. Bershalawat berarti menautkan kesadaran manusia dengan insān kāmil agar langkahnya tidak keluar dari falak amanah. Dengan shalawat, manusia diingatkan bahwa pengelolaan alam bukan hanya soal efisiensi, tetapi adab; bukan hanya kebijakan, tetapi kesucian niat; bukan hanya sains, tetapi hikmah.
Maka ketika Al-Qur’an mengatakan wa kullun fī falakin yasbahūn, ia sedang mengajarkan etika kosmik. Setiap wujud memiliki orbit, batas, dan peran. Ekologi transenden mengundang manusia untuk kembali ke orbitnya sendiri: bukan sebagai penguasa yang serakah, tetapi sebagai hamba yang bersujud. Jika kosmos yasbahūn dalam keteraturan, manusia pun seharusnya yasbahūn dalam keteraturan moral—menekan kecenderungan merusak, merawat yang lemah, menghidupkan yang gersang, dan menahan tangan dari keserakahan.
Di titik inilah sains ekologi menemukan ruhnya, dan ruh menemukan bahasanya. Wahyu memberi arah, itrah memberi teladan, dan cinta menggerakkan tindakan. Ekologi tidak lagi sekadar ilmu tentang lingkungan, tetapi jalan spiritual manusia menuju kesempurnaan bersama seluruh alam semesta dalam bimbingan insān kāmil.
*Penulis adalah Guru Besar Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin
 Prof Khusnul Yaqin merefleksikan gagasan tentang harmoni antara kesadaran manusia, etika ekologis, dan keteraturan alam semesta sebagaimana diisyaratkan dalam Surah Yasin.
Prof Khusnul Yaqin merefleksikan gagasan tentang harmoni antara kesadaran manusia, etika ekologis, dan keteraturan alam semesta sebagaimana diisyaratkan dalam Surah Yasin.

_1-300x169.webp)