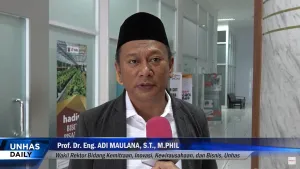Oleh:Khusnul Yaqin*
Universitas, dalam hakikatnya yang terdalam, bukanlah sekadar pabrik pencetak ijazah untuk memenuhi statistik pasar kerja, melainkan arena pengaderan intelektual—suatu majelis tak kasatmata di mana nalar diuji, dikritik, dan dipurnakan. Di ruang inilah mahasiswa bukan hanya dipersiapkan untuk “bekerja”, tetapi ditempa menjadi subjek yang mampu mengolah pengetahuan menjadi kekuatan kreatif dan praksis transformatif. Sebab, tanpa pengaderan intelektual, universitas hanyalah industri sertifikasi, dan mahasiswa hanyalah pekerja magang yang menunggu giliran dimasukkan ke dalam mesin kapitalisme global.
Mengader intelektual di kampus berarti menumbuhkan dialektika yang tak henti-hentinya antara dua poros utama: pengajaran dan penelitian. Pengajaran, apabila sekadar dipahami sebagai transfer informasi, akan segera menjadi monolog steril. Tetapi apabila ia diperkaya dengan dialog—antara dosen dan mahasiswa, antara mahasiswa dengan sesamanya, bahkan antara teks klasik dengan pengalaman empiris—maka pengajaran berubah menjadi arena dialektika. Inilah cara berpikir yang perlu dirawat: keberanian mempertanyakan, keterampilan merunut argumen, dan kepekaan menangkap kontradiksi.
Sebaliknya, penelitian bukanlah sekadar katalogisasi data atau pengumpulan angka statistik, melainkan kerja praksis yang melibatkan tubuh, indera, dan kecermatan metodologis. Di sinilah alat laboratorium memainkan peran sentral. Mahasiswa harus disentuhkan, bahkan ditenggelamkan, dalam dunia laboratorium. Jangan sekali-kali mahasiswa dijauhkan dari alat-alat riset dengan alasan takut rusak. Justru di situlah kaderisasi intelektual diuji: kemampuan menjaga alat sama pentingnya dengan kemampuan menggunakannya. Bagaimana mungkin kita berharap mahasiswa menghasilkan pikiran inovatif, sementara tangan mereka steril dari sentuhan pipet, mikroskop, spektrofotometer atau FTIR?
Laboratorium bukan sekadar ruang teknis, melainkan madrasah kedua setelah ruang kuliah. Jika di ruang kuliah mahasiswa dilatih untuk berpikir, maka di laboratorium mereka dilatih untuk mengerjakan hasil olah pikir. Dua dimensi ini tidak boleh dipisahkan. Seorang intelektual yang hanya berpikir tanpa keterampilan teknis akan terjebak dalam menara gading, sebaliknya yang hanya bisa mengerjakan tanpa horizon berpikir akan terjerembap menjadi teknokrat buta.
Mengader intelektual berarti memadukan kedua dimensi itu. Mahasiswa harus dilatih mengukur sendiri sampel air, menghitung konsentrasi logam, mengoperasikan PCR, menganalisis citra mikroskop atau menentukan polimer mikro plastik dengan FTIR. Proses ini tidak hanya melatih keterampilan tangan, tetapi juga melatih kesabaran, ketelitian, bahkan kerendahan hati: sebab alat laboratorium tidak mentolerir kecerobohan. Kegagalan eksperimen adalah guru yang lebih jujur daripada seribu halaman buku kuliah.
Sering kita mendengar alasan: mahasiswa dijauhkan dari alat laboratorium karena takut rusak. Argumen ini lahir dari logika manajemen birokratis yang lebih mementingkan umur ekonomis peralatan daripada umur intelektual mahasiswa. Padahal, alat yang dijauhkan dari pengguna sejatinya telah mati sejak hari pertama. Alat yang hidup adalah alat yang digunakan, dipelajari, diperbaiki, bahkan kalau perlu rusak—asal kerusakan itu menjadi guru bagi puluhan mahasiswa berikutnya.
Universitas yang sehat tidak takut terhadap kerusakan alat, melainkan takut terhadap kerusakan intelektual. Sebab kerusakan alat dapat diperbaiki dengan servis atau pengadaan, tetapi kerusakan intelektual generasi mahasiswa akan berimplikasi jauh lebih panjang, menular, dan sistemik.
Kata “kader” sering kali diasosiasikan dengan politik. Namun, sejatinya universitas juga merupakan ladang kaderisasi intelektual. Mahasiswa adalah kader ilmu, kader kebudayaan, bahkan kader peradaban. Ia bukan sekadar individu yang menuntut ilmu untuk kepentingan diri, melainkan bagian dari mata rantai panjang sejarah intelektual umat manusia. Maka, kaderisasi intelektual berarti memberi mereka kesempatan untuk “berproses”, bukan hanya “berhasil”.
Proses itu meliputi kebiasaan membaca teks sulit, berdiskusi tanpa akhir, berdebat dengan keberanian argumentatif, serta bersentuhan dengan instrumen laboratorium secara langsung. Semua itu adalah jalan terjal yang harus dilalui. Tanpa jalan terjal, kita tidak sedang mengader intelektual, melainkan hanya menyiapkan buruh intelektual yang patuh.
Banyak universitas hari ini terjebak dalam mentalitas “output pasar kerja”. Akibatnya, visi akademik direduksi menjadi sekadar tabel akreditasi, indikator kinerja, dan kurikulum modular. Mahasiswa diperlakukan seperti konsumen, dosen seperti penyedia jasa, dan laboratorium seperti museum yang boleh dilihat tetapi tidak boleh disentuh.
Krisis ini bukan hanya persoalan teknis, melainkan krisis ontologis: kampus kehilangan jiwanya sebagai tempat pengaderan intelektual. Intelektual yang lahir dari rahim kampus demikian akan rapuh, mudah digilas arus pragmatisme, dan kehilangan kemampuan merumuskan pikiran besar. Padahal, bangsa tidak hanya membutuhkan pekerja, tetapi juga pemikir yang mampu merumuskan ulang arah peradaban.

Ilustrasi universitas adalah pusat pengaderan ilmuwan dan cendekiawan tercerahkan. Melalui dialektika di ruang kuliah dan praksis di laboratorium, mahasiswa ditempa menjadi agen inovasi yang siap menciptakan masa depan bangsa.
Tentu, ada yang berargumen bahwa idealisme semacam ini sulit diwujudkan karena keterbatasan dana, alat, atau SDM. Tetapi keterbatasan justru adalah lahan paling subur untuk kaderisasi intelektual. Mahasiswa yang dilatih untuk berimprovisasi dengan keterbatasan akan lebih tangguh daripada yang dimanja dengan fasilitas berlimpah. Sejarah ilmu pengetahuan penuh dengan kisah penemuan besar yang lahir dari laboratorium sederhana, bahkan garasi rumah.
Yang diperlukan bukanlah fasilitas mewah, melainkan keberanian dosen untuk membuka akses, keseriusan dalam memberikan pelatihan, dan kesabaran dalam membimbing mahasiswa. Dari kombinasi itu lahirlah intelektual yang mandiri, inovatif, dan berani mengambil risiko.
Akhirnya, mengader intelektual di kampus bukanlah proyek jangka pendek, melainkan investasi bangsa. Mahasiswa hari ini adalah penentu arah bangsa esok. Jika mereka miskin keterampilan laboratorium, maka mereka akan miskin kemampuan inovatif. Jika mereka miskin dialektika berpikir, maka mereka akan miskin visi peradaban
Sebaliknya, jika universitas mampu memadukan ruang kuliah sebagai arena dialektika dan laboratorium sebagai arena praksis, maka akan lahir generasi intelektual yang bukan hanya bisa bekerja, tetapi juga bisa mencipta, bukan hanya bisa mengikuti, tetapi juga bisa memimpin.
Mengader intelektual di kampus berarti menolak menjadikan universitas sebagai pabrik buruh intelektual. Ia adalah upaya membangkitkan kembali hakikat universitas sebagai pengaderan intelektual, di mana pengajaran dan penelitian berkelindan, di mana mahasiswa disentuhkan dengan teks sekaligus dengan alat, di mana kesalahan dipandang sebagai guru, dan keterbatasan sebagai peluang.
Universitas yang berani mempercayakan laboratoriumnya kepada mahasiswa, yang berani membuka ruang dialog kritis, yang berani mempertaruhkan kenyamanan demi pertumbuhan intelektual, akan melahirkan kader-kader yang tidak hanya bekerja untuk dirinya, tetapi berpikir dan berkarya untuk bangsanya. Dan hanya universitas semacam itulah yang layak disebut universitas sejati.
Alat-alat laboratorium bukanlah berhala yang disembah, sedemikian rupa takut menjadi rusak, tetapi mereka adalah penggerak inovasi peradaban. Berikan kesempatan yang sangat luas kepada mahasiswa untuk berlaboratorium demi kontinuitas peradaban manusia yang maju.
*Penulis adalah Guru Besar pada Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin