
Dosen Psikologi Unhas Dwiana Fajriati Dewi SPsi MSc. (dok unhas.tv)
Menurut teori psikologi kerja, ada empat aspek yang membuat karyawan merasa puas: Task Significance – Pekerjaan terasa penting dan berdampak.
Variety – Tugas yang beragam mencegah kebosanan. Autonomy – Kebebasan dalam menjalankan tugas tanpa kontrol berlebihan. Feedback – Apresiasi, baik verbal maupun non-verbal, yang membuat karyawan merasa dihargai.
“Seringkali feedback diabaikan. Padahal, apresiasi sederhana bisa memotivasi lebih dari sekadar uang,” tegas Dwi.
Menariknya, dalam teori psikologi, uang hanya mampu mengubah kondisi dari dissatisfaction menjadi netral. Untuk mencapai satisfaction, dibutuhkan faktor lain seperti penghargaan, kesempatan berkembang, dan dukungan rekan kerja.
Selain atasan, dukungan rekan kerja berperan besar dalam mencegah quiet quitting. “Teman kerja yang suportif dapat mengurangi tekanan. Sebaliknya, lingkungan toxic membuat pekerja cepat unmotivated,” jelasnya.
Di Indonesia, pekerja sering dibatasi kreativitasnya karena struktur kerja yang kaku. Ketika kebebasan berkarya terhambat, motivasi pun menurun. Dalam kondisi ini, pekerja bisa mencari aktivitas di luar pekerjaan—bergabung dengan komunitas, olahraga, atau hobi lain—untuk menjaga keseimbangan hidup.
Dampak Quiet Quitting: Positif dan Negatif
Quiet quitting memiliki dua sisi. Di satu sisi, ia melindungi pekerja dari burnout. Di sisi lain, bisa menghambat pengembangan diri dan karir jangka panjang. “Ketika kita mengurangi usaha, otomatis kesempatan belajar dan promosi juga berkurang,” ungkap Dwi.
Hal ini juga berlaku pada level atasan. Jika pimpinan menerapkan quiet quitting, ia memberi contoh buruk bagi bawahannya, yang akhirnya ikut menurunkan standar kerja.
Agar quiet quitting tidak meluas, perusahaan harus memperhatikan keseimbangan antara tuntutan kerja dan kapabilitas karyawan. “Jangan hanya memberi beban tinggi tanpa pelatihan yang memadai. Capacity building harus sejalan dengan demand,” kata Dwi.
Komunikasi dua arah juga sangat penting. Feedback harus diberikan segera, baik ketika karyawan berhasil maupun ketika melakukan kesalahan. “Timing itu krusial. Apresiasi atau koreksi yang terlambat kehilangan makna,” ujarnya.
Di penghujung diskusi, Dwi menegaskan bahwa quiet quitting bukanlah kemalasan, melainkan reaksi wajar terhadap ketidakadilan dalam dunia kerja. “Fenomena ini terjadi ketika input dan output tidak seimbang. Wajar jika pekerja mencari keseimbangan untuk menjaga kesehatan mentalnya,” jelasnya.
Sebagai penutup, ia memberikan pesan untuk perusahaan: “Karyawan bukan hanya butuh uang. Untuk membuat mereka puas, perusahaan harus memperhatikan task significance, autonomy, feedback, dan coworker support. Lingkungan kerja yang sehat dan suportif akan membuat karyawan lebih termotivasi.”
Quiet quitting bukanlah sekadar tren, tetapi sinyal bahwa dunia kerja harus berubah. Bukan hanya produktivitas yang perlu diperhatikan, melainkan juga kesejahteraan psikologis para pekerjanya.
Dalam dunia kerja yang sehat, tidak perlu ada perlawanan diam-diam, karena setiap orang merasa dihargai, didukung, dan berkembang bersama. (*)

-300x167.webp)
-300x169.webp)

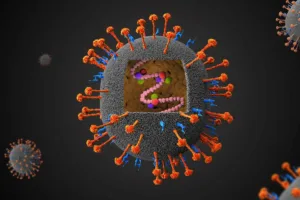
, Dokter Anak Konsultan Tumbuh Kembang dan Pediatri Sosial (1)_1-300x173.webp)





