UNHAS.TV - Pernahkah Anda merasa telah memberikan segalanya untuk pekerjaan, namun tetap saja kurang dihargai?
Lembur tanpa upah, tuntutan untuk selalu siap kapan saja, hingga akhirnya membuat Anda lupa bahwa diri ini adalah manusia dengan batas kemampuan.
Dari keresahan itulah, lahir fenomena baru di dunia kerja yang kini ramai diperbincangkan: quiet quitting. Fenomena ini tidak muncul tanpa sebab.
Dalam program Unhas Speak Up di studio Unhas TV, Dwiana Fajriati Dewi, S.Psi., M.Sc., dosen Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin membahas mengenai quiet quitting yang kini menjadi sorotan di kaum Gen Z.
Lantas apa itu sebenarnya Quiet Quitting? Pandangan Dwiana yang mendalami psikologi industri dan organisasi, quiet quitting bukan berarti berhenti bekerja secara fisik, melainkan hanya bekerja sesuai porsi job description tanpa memberikan usaha ekstra.
“Dalam teori kinerja, ada tiga jenis performa: task performance (sesuai jobdesk), contextual performance (di luar jobdesk), dan counterproductive performance (bertentangan dengan aturan). Quiet quitting terjadi ketika karyawan hanya menjalankan task performance,” jelasnya.
Fenomena ini mulai populer pada 2022, setelah pandemi Covid-19. Pandemi mempercepat adopsi teknologi, membuat pekerjaan bisa diakses kapan saja, di mana saja.
Akibatnya, batas waktu kerja menjadi kabur, tuntutan meningkat, dan pekerja sering merasa terkuras. “Dulu rapat malam itu jarang terjadi, tapi setelah pandemi, rapat online jam berapa pun bisa dilakukan,” tambah Dwiana.
Antara Hustle Culture dan Quiet Quitting
Fenomena ini kontras dengan hustle culture, budaya kerja yang mendorong karyawan untuk selalu produktif, bekerja di luar jam, bahkan mengorbankan waktu pribadi demi karier.
Bagi sebagian orang, quiet quitting dianggap sebagai tanda kemalasan. Namun, bagi generasi muda, khususnya Gen Z, ini adalah bentuk perlawanan untuk menjaga kesehatan mental dan keseimbangan hidup.
“Sejak 2003, definisi karier berubah. Karier tidak lagi hanya soal uang dan jabatan, tetapi juga psychological wellbeing. Orang mencari kesejahteraan psikologis, bukan sekadar gaji tinggi,” terang Dwiana.
Generasi Z kerap dicap malas atau gampang resign. Namun, Dwiana melihat hal ini dari perspektif yang berbeda. Menurutnya, perubahan nilai dalam memandang karier dan tingginya paparan informasi tentang kesehatan mental membuat generasi ini lebih berani menolak sistem kerja yang tidak sehat.
“Mereka tidak takut pindah kerja karena mengutamakan work-life balance. Banyak di antara mereka juga mendapat dukungan orang tua yang mapan, sehingga lebih leluasa memilih,” katanya.
Selain itu, pengalaman massal layoff dari perusahaan besar menambah kesadaran bahwa pekerjaan tidak selalu stabil, sehingga menjaga kesehatan mental menjadi prioritas.
Unmotivated, Bukan Malas
>> Baca Selanjutnya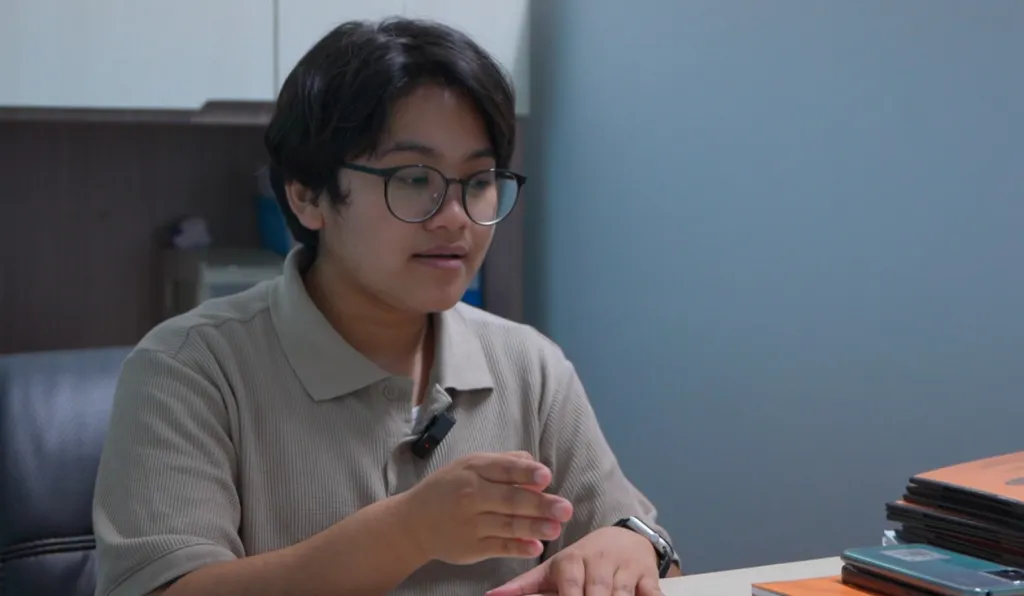




 MHPE (2)-300x169.webp)

-300x185.webp)




