Oleh: Khusnul Yaqin*
Kenaikan suhu global yang berkelindan dengan peningkatan emisi dan meluapnya produksi plastik bukan sekadar grafik yang bergerak naik, melainkan penanda bahwa realitas ekologis sedang mengalami tekanan ganda yang berlipat. Pada titik tertentu, manusia menyadari bahwa krisis tidak lagi berwajah tunggal. Ia menjadi rangkap, saling menyusupi, dan akhirnya membentuk semacam medan gaya yang menyeret seluruh sistem kehidupan ke dalam lingkaran stres berkesinambungan. Tiga di antaranya—pemanasan global, emisi bahan pencemar, dan mikroplastik—merupakan representasi paling nyata dari dunia yang kehilangan keseimbangan antara intensitas produksi dan ketahanan ekologis. Ketiganya bekerja seperti tiga simpul dalam satu jaringan gangguan eksistensial yang tak lagi dapat diurai secara parsial.
Pemanasan global mengacaukan ritme termal planet, mencairkan pola-pola yang dahulu stabil. Emisi bahan pencemar menambah lapisan gangguan kimiawi yang menyelinap ke udara, air, tanah, bahkan tubuh organisme. Sementara mikroplastik—partikel kecil yang pada awalnya dianggap remeh—telah menembus dimensi biologis hingga tingkat sel, menjelma menjadi residu antropogenik yang memasuki ruang terdalam metabolisme suatu organisme. Ketiganya tidak bergerak sendiri-sendiri; setiap peningkatan pada satu variabel memperkuat daya rusak variabel yang lain. Inilah fase ketika lingkungan tidak hanya menderita secara fisik, tetapi juga secara ontologis, karena sistem pendukung kehidupan kehilangan derajat kebebasan untuk menahan guncangan-guncangan baru.
Dalam kondisi seperti itu, monitoring lingkungan tidak bisa lagi dipahami sebagai kegiatan rutin mengukur parameter. Monitoring harus bertransformasi menjadi struktur pengetahuan yang hidup, suatu upaya membaca gejala ekologis layaknya membaca detak jantung sebuah organisme yang sedang melemah. Di sinilah biomonitoring berbasis biomarker menemukan relevansi filosofisnya. Biomarker bukan sekadar indikator laboratorium; ia adalah bahasa yang diucapkan oleh organisme ketika mengalami tekanan. Respons molekuler, fisiologis, atau perilaku organisme merupakan bentuk kesaksian biologis yang sering kali muncul jauh lebih awal sebelum kerusakan lingkungan terdeteksi secara kasat mata. Dalam pemahaman ini, biomarker adalah epistemologi ekologis yang memungkinkan manusia memahami jeritan halus ekosistem.
Penguatan biomonitoring mutlak diperlukan karena ketiga stres besar lingkungan ini bekerja dalam ketidakpastian. Pemanasan global memodifikasi kecepatan reaksi kimia, mempercepat dan meningkatkan toksisitas, serta menciptakan sinergi baru antara polutan. Emisi bahan pencemar mengubah struktur komunitas biota, menggeser dominansi spesies, dan merombak jejaring trofik. Mikroplastik, dengan segala sifat fisikokimia yang rapuh-padat, menjadi medium pengangkut logam toksik, patogen, dan senyawa organik persisten, memperkenalkan bentuk baru pencemaran yang tidak stabil tetapi sangat memengaruhi organisme. Dalam dunia yang berlapis-lapis kerumitannya ini, biomarker menjadi kompas yang membantu manusia menafsirkan arah perubahan.
Namun, monitoring dan biomonitoring bukanlah tujuan akhir. Keduanya menjadi peringatan epistemik yang seharusnya memicu koreksi pada perilaku, kebijakan, dan struktur produksi. Pengurangan aktivitas manusia yang mempercepat ketiga stres lingkungan itu bukan lagi pilihan moral, melainkan kebutuhan ontologis agar bumi tidak jatuh ke titik di mana sistemnya tak lagi memiliki kemampuan pulih. Masalahnya adalah, manusia modern telah terjebak dalam paradoks: ia mengetahui bahwa tindakannya merusak, tetapi ia tidak mampu membatasi dirinya karena struktur ekonomi, teknologi, dan politik bergerak dengan logika ekspansi tanpa batas. Maka reduksi aktivitas tidak bisa hanya dimaknai sebagai pengurangan proses industri atau regulasi teknokratis; ia memerlukan transformasi cara pandang terhadap makna keberadaan.
Di sinilah kesadaran ekologi transenden menawarkan kerangka yang lebih dalam. Kesadaran ini tidak bertumpu pada instrumen teknis, tetapi pada perasaan bahwa kehidupan adalah jaringan yang saling berkelindan, sehingga gangguan pada satu simpul beresonansi ke seluruh simpul lain. Dalam ekologi transenden, manusia tidak dilihat sebagai pusat, tetapi sebagai bagian dari arus keberadaan yang lebih luas. Sikap terhadap lingkungan bukan sekadar sikap etis, tetapi ekspresi metafisik tentang bagaimana manusia memahami dirinya di dalam kosmos. Ketika seseorang memahami bahwa keberadaannya hanya mungkin karena ada jejaring lain yang menopangnya—dari plankton, fitomikroba, iklim, hingga molekul air—maka perubahan perilaku tidak muncul dari rasa bersalah ekologis, tetapi dari rasa keterhubungan eksistensial.

Ilustrasi ini menggambarkan suasana kontemplatif yang merefleksikan gagasan Prof. Khusnul Yaqin dalam opininya “Sinergitas Stres Lingkungan dan Monitoring Bernapas Ekologi Transenden.”
Perubahan perilaku berlandaskan kesadaran seperti itu memiliki kekuatan yang lebih tahan lama dibanding pendekatan hukum atau ekonomi. Ia bekerja seperti penyadaran bahwa tubuh manusia dan tubuh bumi bukan dua entitas terpisah, tetapi dua manifestasi dari satu kontinuitas kehidupan. Dengan perspektif transenden ini, pengurangan konsumsi plastik bukan sekadar pengurangan sampah, tetapi bagian dari latihan melepaskan diri dari obsesi material. Pembatasan emisi bukan sekadar teknis, tetapi perjalanan menuju kesederhanaan ontologis. Menghentikan pemborosan energi tidak sekadar kebijakan, tetapi cara untuk menyesuaikan ritme hidup dengan ritme alam yang kini sedang menua.
Tiga stres lingkungan tadi pada akhirnya mengajarkan satu hal penting: krisis ekologis adalah krisis relasi. Relasi antara manusia dan alam telah mengalami disonansi epistemik yang panjang. Pengetahuan ilmiah berjalan, tetapi kesadaran moral dan spiritual tertinggal. Teknologi meningkat, tetapi empati ekologis merosot. Dengan kata lain, monitoring dan biomonitoring dapat memberi data, tetapi tidak dapat memaksa manusia merekonstruksi kesadaran. Oleh karena itu, tanggung jawab terbesar bukan sekadar menghasilkan grafik dan indikator, tetapi menata ulang struktur nilai yang mengatur perilaku manusia.
Di masa depan, keberhasilan menghadapi krisis ekologis tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan peralatan deteksi, tetapi oleh kedalaman kesadaran yang menggerakkan perubahan. Monitoring diperlukan, biomarker dibutuhkan, regulasi tak terhindarkan, tetapi semuanya akan menjadi kurang bernilai jika manusia terus mempertahankan pola hidup yang menambah tekanan pada bumi. Kesadaran ekologis transenden, meski tampak abstrak, justru menawarkan kedalaman makna yang mampu menembus lapisan-lapisan kebiasaan destruktif.
Dengan demikian, pemanasan global, emisi bahan pencemar, dan mikroplastik bukan hanya persoalan ilmiah semata, tetapi cermin dari krisis makna manusia modern. Ketiganya menjadi pengingat bahwa bumi adalah entitas yang bernapas, merasakan, dan merespons, sementara manusia harus kembali mempelajari seni mendengar denyut halus kehidupan yang selama ini terabaikan. Hanya ketika manusia belajar kembali memaknai keberadaan, barulah ketiga stres lingkungan ini dapat diperlambat, dan bumi mendapatkan ruang untuk pulih dari luka-lukanya yang semakin dalam.**
Penulis, Guru Besar pada Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan
 Prof. Khusnul Yaqin membahas pandangannya tentang “Sinergitas Stres Lingkungan dan Monitoring Bernapas Ekologi Transenden.”
Prof. Khusnul Yaqin membahas pandangannya tentang “Sinergitas Stres Lingkungan dan Monitoring Bernapas Ekologi Transenden.”
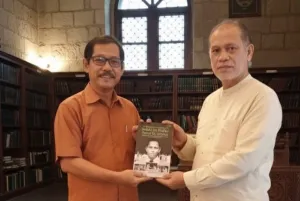

-300x188.webp)
-300x200.webp)







