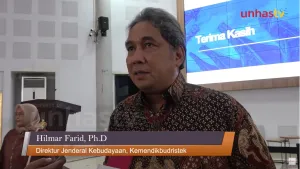Sabirin juga menunjukkan bahwa manuskrip tasawuf Buton banyak merujuk pada karya-karya besar ulama klasik, seperti al-Qushayri, al-Suhrawardi, dan Syekh al-Samman sendiri.
Namun menariknya, para penulis lokal Buton tidak sekadar menerjemah atau menyalin. Mereka menginterpretasikan, menyesuaikan dengan konteks sosial dan budaya lokal. Di sinilah terjadi proses yang disebut Sabirin sebagai “pembaruan dalam kelokalan” atau localized renewal of Islam.
Politik Spiritual: Kesultanan Buton dan Adab Sufi
Dalam manuskrip-manuskrip itu, tersirat pula hubungan erat antara tasawuf dan kekuasaan. Kesultanan Buton dikenal sebagai kesultanan yang berbasis konstitusi Murtabat Tujuh dan Sarana Wolio, yang merupakan tata hukum lokal bercampur nilai Islam.
Tarekat Sammaniyah berperan menanamkan nilai moral dalam struktur kekuasaan. Para pemimpin dianggap sebagai wali masyarakat, bukan sekadar pejabat administratif.
BACA: Pusar Perahu Buton dalam Tinjauan Antropolog Australia
Kepatuhan rakyat kepada Sultan tak sekadar tunduk pada hukum, tetapi merupakan bagian dari ketaatan spiritual. Dan ketika pemimpin menyimpang, masyarakat punya hak untuk mengingatkan. Di sinilah peran tasawuf terlihat sebagai jembatan antara dunia dan akhirat, antara negara dan rakyat, antara struktur dan nurani.
“Sebagaimana para sahabat memuliakan Nabi, begitu pula masyarakat Buton diajarkan memuliakan pemimpin yang adil,” tulis Sabirin, merujuk pada panduan adab dalam kitab ‘Awarif al-Ma‘arif karya al-Suhrawardi yang sering dikutip dalam naskah Buton.
Menghidupkan Kembali Jalan Sunyi
Karya Sabirin bukan sekadar laporan akademik; ia adalah panggilan. Bahwa dalam zaman digital, spiritualitas yang bersumber dari manuskrip tua masih menyimpan kekuatan menyembuhkan. Bahwa jalan tasawuf, yang tenang dan kontemplatif, masih relevan untuk menjawab kebingungan identitas dan kegersangan batin masyarakat modern.
Buton, dengan manuskrip-manuskripnya, bukan sekadar lokasi geografi. Ia adalah lanskap spiritual, tempat di mana huruf-huruf Arab Melayu menari di atas lembaran kertas tua, menghidupkan kembali semesta makna yang nyaris tenggelam dalam hiruk-pikuk dunia modern.
Di sana, Islam tidak hadir sebagai konstruksi institusional semata—ia menjelma menjadi nafas budaya, membentuk cara pandang, cara merasa, dan cara hidup masyarakatnya.
Agama tidak ditempatkan di ruang terpisah dari keseharian, melainkan mengalir dalam tutur kata, aturan adat, hingga sikap hormat kepada sesama. Doa dan dzikir tidak hanya bersemayam di masjid atau mushalla, tetapi menyatu dalam kegiatan panen, dalam proses musyawarah, bahkan dalam tatanan pemerintahan Kesultanan.
Tasawuf bukan sebatas wacana teologis yang tinggi di awang-awang, tetapi menjadi kerangka kerja etis yang membimbing relasi sosial dan kepemimpinan.
Manuskrip Buton adalah saksi dari proses tersebut, lembaran-lembaran sunyi yang sesungguhnya tidak pernah diam. Di setiap aksara yang ditorehkan para ulama dan sufi lokal, terkandung semangat untuk menyelaraskan langit dan bumi, wahyu dan adat, zikir dan kerja.
Seperti daun yang tak lelah jatuh dari pohon hikmah, naskah-naskah itu terus hadir dalam setiap musim perubahan, mengingatkan manusia bahwa agama bukan hanya keyakinan, tetapi laku panjang dan jalan batin yang menuntun manusia dari gelap menuju terang.
*Penulis adalah blogger, peneliti, dan digital strategist. Lulus di Unhas, UI, dan Ohio University. Kini tinggal di Bogor, Jawa Barat.