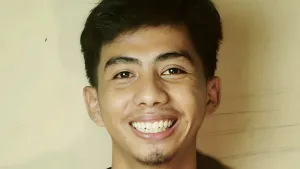Oleh: Mursalim Nohong*
Di tengah gelombang perubahan global—mulai dari krisis iklim, transformasi digital, ketegangan energi, hingga tekanan sosial-ekonomi—muncul satu pertanyaan mendasar: apakah kita akan menunggu masa depan terjadi, ataukah ikut membentuknya?
Pertanyaan ini menjadi semakin relevan saat kita menengok ke sebuah daerah yang kaya akan sumber daya alam dan kebudayaan seperti Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan.
Sebuah kabupaten yang tak hanya dikenal lewat jejak sejarah dan jejak keislaman, tetapi juga lewat potensi besar di sektor pertanian, energi terbarukan, dan kekuatan sumber daya manusianya.
Sidrap bukan sekadar wilayah administratif. Ia adalah tanah warisan nilai, tanah perjuangan, dan simbol transformasi. Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, identitas agraris Sidrap begitu kuat.
Namun, yang membedakannya dari banyak daerah lain adalah langkah-langkah progresif yang mulai diambil. Salah satunya adalah hadirnya Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) terbesar di Asia Tenggara—sebuah penanda bahwa Sidrap tak sekadar menanti perubahan, tetapi telah memulai peran sebagai pelaku dalam transformasi energi nasional.
Namun, pembangunan infrastruktur saja tidak cukup. Masa depan yang berkelanjutan hanya mungkin terwujud jika pembangunan karakter, inovasi berbasis kearifan lokal, dan pengelolaan sumber daya yang adil dan lestari ikut menyertainya.
Lalu, di persimpangan sejarah ini, muncul kembali pertanyaan yang menuntut jawaban nyata: apakah Sidrap akan menjadi penonton dalam kancah perubahan, atau mengambil peran aktif sebagai penggerak masa depan yang berkelanjutan?
Menunggu Masa Depan atau Menyusunnya?
Dalam praktik pembangunan daerah, terlalu sering kita melihat sikap menunggu: menunggu instruksi dari pusat, menunggu aliran dana, menunggu investor datang. Sikap ini menjadi semacam kebiasaan yang pelan tapi pasti menyeret pada stagnasi—terutama di tengah tekanan global yang menuntut kecepatan dan efisiensi.
Sidrap tak bisa lagi berdiam diri. Perubahan iklim telah mengganggu siklus pertanian. Anak-anak muda generasi Z meninggalkan kampung halaman, melepaskan warisan nilai yang ditanamkan para leluhur seperti Nene’ Mallomo. Ketergantungan pada satu komoditas seperti beras tanpa diversifikasi membuat perekonomian lokal rapuh di tengah fluktuasi harga global.
Kini saatnya mengubah paradigma. Sidrap harus ditempatkan sebagai subjek perubahan, bukan objek pembangunan. Masa depan tidak datang sebagai durian runtuh. Ia dibentuk melalui kesadaran, strategi, dan aksi nyata—dari desa hingga ke tingkat kabupaten.
Keberlanjutan di Tanah Kelahiran
Wacana keberlanjutan hari ini tidak bisa lagi hanya bicara soal lingkungan. Ia adalah soal ketahanan hidup lintas sektor. Di Sidrap, isu keberlanjutan mencakup:
Pertama, keberlanjutan lingkungan. Bagaimana menjaga Danau Sidenreng dari pencemaran? Bagaimana mencegah banjir akibat alih fungsi lahan? Akankah hutan-hutan di pegunungan tetap hijau atau berubah menjadi korban ekspansi? Ini semua menuntut keterlibatan aktif, bukan pasif menunggu.
Kedua, keberlanjutan sosial. Apakah nilai-nilai luhur Nene’ Mallomo masih mengakar dalam jiwa generasi muda? Ataukah budaya lokal telah digantikan oleh budaya instan yang serba cepat?
Ketiga, keberlanjutan ekonomi. Mampukah Sidrap bertahan sebagai penghasil pangan ketika sawah tergantikan oleh properti? Mampukah petani naik kelas sebagai pelaku rantai nilai, bukan sekadar produsen bahan mentah?
Riset Yusriah Arief (2022) menunjukkan bahwa alih fungsi lahan di Sidrap, terutama di Maritengngae dan Panca Rijang, terus meningkat akibat tekanan ekonomi dan pertumbuhan penduduk. Lahan-lahan pertanian dijual demi kebutuhan sesaat, mengancam ketahanan pangan masa depan.
Keempat, keberlanjutan energi dan inovasi. Hadirnya PLTB seharusnya tak membuat warga hanya menjadi penonton. Pertanyaannya: apakah masyarakat lokal turut dilibatkan sebagai pelaku dalam ekonomi hijau?
Kelima, keberlanjutan spiritual dan moral. Nilai-nilai religius di Sidrap adalah kekuatan yang tak boleh diabaikan. Tapi nilai bukan sekadar untuk dikenang; ia harus menjadi cahaya yang menuntun pembangunan jiwa. Globalisasi dan modernisasi yang tak disaring telah membuat banyak orang kehilangan kompas moral. Maka reorientasi dan reaktualisasi nilai menjadi sangat mendesak.
Jika ukuran keberhasilan hanya ekonomi, maka kita lupa bahwa ekonomi terus berubah. Yang lestari adalah nilai yang menuntun arah perubahan itu.
Strategi Menuju Masa Depan: Empat Pilar Transformasi
Agar tidak hanya menunggu, Sidrap perlu strategi jangka panjang berbasis empat pilar:
Pertama, pendidikan dan literasi masa depan. Kurikulum pendidikan di Sidrap harus melampaui standar normatif nasional, dengan memasukkan pendidikan lingkungan lokal, literasi teknologi, dan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal—termasuk ajaran Nene’ Mallomo—ke dalam ruang kelas dari SD hingga SMP.