Oleh: Khusnul Yaqin*
Di Indonesia, setiap kali berganti menteri, berganti pula jargon kebijakan. Nadiem Makarim datang dengan “Merdeka Belajar”, yang bergaung sebagai simbol kebebasan akademik dan inovasi pendidikan. Kini, penggantinya membawa jargon baru: “Berdampak.” Sekilas kata ini terdengar positif, modern, dan komunikatif. Namun bila diselami secara konseptual, kata “dampak” menyimpan ambiguitas yang berpotensi menyesatkan arah riset dan pendidikan tinggi.
“Dampak” dalam bahasa Indonesia bukanlah sinonim bagi “manfaat.” Ia adalah kata yang netral secara moral: sesuatu bisa berdampak baik, bisa juga berdampak buruk. Ketika Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menjadikan “berdampak” sebagai visi, pertanyaannya sederhana namun mendasar: dampak seperti apa yang dimaksud? Bila tak dijelaskan, jargon ini berisiko menjelma jadi slogan administratif yang sibuk memoles citra, bukan membangun arah substantif bagi ilmu dan teknologi.
Kata “berdampak” dipilih karena terdengar progresif, seolah mengundang semangat perubahan. Namun jargon yang baik seharusnya lahir dari refleksi epistemologis—hasil perenungan tentang bagaimana ilmu bekerja dan untuk siapa ilmu itu berguna. Dalam konteks kebijakan publik, sebuah jargon bukan sekadar alat branding; ia adalah arah ideologis.
Masalahnya, “berdampak” tidak punya kejelasan epistemik. Ia tidak menjelaskan apakah dampak yang diinginkan bersifat ekonomi, sosial, ilmiah, ekologis, atau etis. Akibatnya, setiap orang bisa mengklaim dirinya telah “berdampak” tanpa ukuran yang sama. Penelitian yang merusak ekosistem pun dapat dianggap berdampak selama menghasilkan publikasi tinggi atau paten baru. Kebijakan pendidikan yang menghapus kesetaraan sosial juga bisa disebut berdampak karena “mengubah sistem.” Ambiguitas inilah yang membuat jargon “berdampak” tampak inklusif secara retorik tetapi kosong secara konseptual.
Dalam filsafat bahasa, Ludwig Wittgenstein pernah menulis bahwa “batas bahasaku adalah batas duniaku.” Ketika kementerian menggunakan kata “berdampak,” ia sesungguhnya sedang membatasi cara kita berpikir tentang pendidikan dan riset. Kata tersebut menormalisasi logika hasil akhir ketimbang proses ilmiah. Kita dipaksa menilai ilmu dari seberapa “terlihat” pengaruhnya, bukan dari seberapa mendalam kejujurannya.
Dalam konteks universitas, logika “berdampak” dapat menggeser orientasi riset dari truth-seeking menjadi attention-seeking. Peneliti akan berlomba menciptakan efek yang dapat diukur secara cepat—bukan pemahaman jangka panjang yang membangun peradaban. Ilmu yang tenang, teoritis, dan reflektif akan dianggap tidak berdampak. Padahal, sejarah menunjukkan, teori yang tampak “tidak berguna” sering kali melahirkan perubahan besar di masa depan. Lihatlah penemuan relativitas Einstein, teori evolusi Darwin, atau riset dasar Watson-Crick—semuanya tak “berdampak” pada awalnya, namun merevolusi dunia.
Dalam percakapan sehari-hari, orang sering berkata “dampak negatif dari kebijakan ini cukup besar.” Artinya, kita sadar bahwa dampak bukanlah sinonim dari manfaat. Jika demikian, mengapa kementerian menggunakannya seolah selalu positif? Bahasa publik seharusnya berhati-hati, sebab kata yang ambigu dapat menciptakan bias dalam kebijakan.
Ketika universitas diwajibkan untuk “berdampak,” apakah yang dinilai adalah kebermanfaatan sosial atau sekadar perubahan? Bila sebuah riset menciptakan kecanduan teknologi, menghapus lapangan kerja, atau mempercepat ketimpangan sosial, itu juga dampak—tetapi jelas bukan yang diinginkan. Maka sebelum slogan “berdampak” dipakai dalam setiap proposal penelitian dan laporan tahunan, harus ada kejelasan normatif: dampak seperti apa yang hendak dibangun? Baik atau buruk? Positif atau destruktif?
Tanpa itu, kita sedang membuka ruang bagi dampak yang disfungsional: penelitian yang mengejar efek sesaat, proyek sosial yang hanya berorientasi pada pencitraan, dan kebijakan pendidikan yang sibuk mengukur hasil tapi kehilangan makna kemanusiaan.
Pergantian jargon tiap menteri menunjukkan bahwa pendidikan tinggi di Indonesia sering kehilangan kontinuitas gagasan. “Merdeka Belajar” sejatinya punya semangat: membebaskan dosen dan mahasiswa dari birokrasi yang mengekang. Namun, ketika berganti kepemimpinan, semangat itu belum matang—langsung diganti dengan “Berdampak.” Pergantian istilah ini seperti mengganti baju tanpa mengganti tubuh. Substansi belum selesai, tetapi kulitnya sudah berubah. Jargon baru seharusnya memperdalam yang lama, bukan menghapusnya. Jika “Merdeka Belajar” menekankan kebebasan berpikir, maka “Berdampak” seharusnya menegaskan tanggung jawab atas kebebasan itu. Sayangnya, yang terjadi justru sebaliknya: “Berdampak” menjadi kata serba bisa yang kehilangan arah etis.

Dua Jargon, Satu Arah? Pergantian jargon kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia—dari "Merdeka Belajar" ke "Berdampak"—seringkali hanya mengganti kulit tanpa memperdalam substansi. Ilustrasi ini menunjukkan bagaimana fokus dari kebebasan berpikir (Merdeka Belajar) bergeser ke ambiguitas hasil (Berdampak). Kata 'Berdampak' netral secara moral. Tanpa kejelasan etis, dampak bisa bermakna baik maupun buruk, berpotensi menggeser riset dari truth-seeking menjadi attention-seeking. Jargon baru seharusnya memperdalam makna, bukan menghapus semangat yang lama. Yang dibutuhkan adalah konsistensi visi dan kejelasan konsep, bukan sekadar gema kosong yang mudah direduksi menjadi indikator administratif.
Di tangan birokrasi, jargon sering berubah menjadi instrumen penilaian administratif. Maka, “berdampak” bisa disulap menjadi format laporan: seberapa banyak kegiatan, peserta, atau media yang menulis tentangnya. Inilah bahaya ketika bahasa kebijakan tidak berakar pada filsafat ilmu—ia mudah direduksi menjadi indikator.
Untuk keluar dari ambiguitas, kata “dampak” perlu diberi isi moral. Ia harus dipahami sebagai hasil yang baik secara etis dan konstruktif secara sosial. Bukan sekadar perubahan, tapi perubahan yang memanusiakan. Riset yang berdampak, misalnya, bukan hanya riset yang menghasilkan teknologi baru, tetapi yang memastikan teknologi itu tidak merusak ekosistem dan memperlebar ketimpangan. Pendidikan yang berdampak bukan hanya yang mencetak lulusan cepat kerja, tetapi yang membentuk kesadaran kritis dan karakter kemanusiaan yang mulia.
Dalam tradisi ilmu, kata “impact” dalam bahasa Inggris sendiri tidak otomatis bermakna positif. Namun lembaga-lembaga besar seperti OECD atau UNESCO menjelaskan bahwa research impact harus mencakup relevance, ethics, dan sustainability. Artinya, dampak tanpa arah moral hanyalah gerakan tanpa jiwa. Indonesia seharusnya belajar dari situ: jangan menjadikan kata “berdampak” sekadar bunyi modern, tetapi isi dengan nilai kemanusiaan dan keberlanjutan.
Bahasa kebijakan bukan sekadar alat komunikasi, tetapi alat berpikir kolektif. Jika kementerian mengulang kata “berdampak” tanpa membedah maknanya, maka publik pun akan terbiasa berpikir dangkal: bahwa segala sesuatu cukup dinilai dari “hasilnya.” Akibatnya, ekosistem riset akan makin pragmatis, kehilangan keberanian berpikir jangka panjang.
Kita seharusnya kembali pada logika ilmiah yang lebih mendasar: ilmu bukan diukur dari besarnya efek, tetapi dari kedalaman dan ketepatan nalar. Dampak hanyalah konsekuensi, bukan tujuan utama. Ilmu yang baik akan menghasilkan dampak yang baik—tetapi tidak semua hal yang berdampak adalah ilmu yang baik.
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi perlu berhenti memproduksi jargon tanpa nalar epistemologis. Masyarakat ilmiah tidak butuh kata baru setiap kali kursi menteri berganti; yang dibutuhkan adalah konsistensi visi dan kejelasan konsep. Jika benar ingin menjadikan pendidikan tinggi “berdampak positif,” maka yang perlu dilakukan bukan mengganti istilah, melainkan memperdalam makna: mendefinisikan apa itu dampak baik, menetapkan standar etis, dan menanamkan kesadaran bahwa pengetahuan sejati tidak selalu tampak gemerlap di permukaan.
Tanpa itu semua, kata “berdampak” hanyalah gema kosong di ruang birokrasi—menggembung dalam pidato, tapi hampa dalam nalar.
*Penulis adalah Guru Besar pada Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin
 undefined
undefined
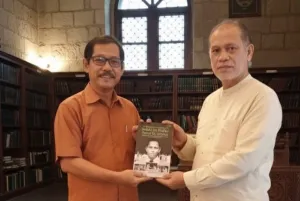






-300x159.webp)



