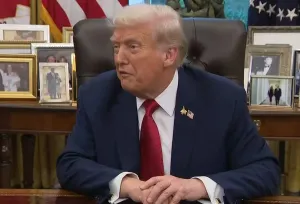Guru Besar Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Unhas, Prof Dr Ir Mimi Arifin MSi. (dok unhas.tv)
Dalam konsep PBB yang dicanangkan sejak 2015, permukiman berkelanjutan menjadi bagian dari Sustainable Development Goals (SDGs), tepatnya pada Tujuan ke-11: Mewujudkan kota dan permukiman yang inklusif, tangguh, aman, dan berkelanjutan.
“Kalau dilihat dari aturan nasional sebenarnya kita sudah memenuhi banyak standar,” jelas Mimi. “Tapi kata ‘berkelanjutan’ itu menuntut sesuatu yang lebih: bukan hanya bangunan dan infrastruktur, tapi juga rasa kebersamaan.”
Ia menjelaskan bahwa permukiman yang berkelanjutan bukan sekadar kumpulan rumah dengan prasarana lengkap. “Ia harus layak huni, mampu menjadi tempat pembinaan keluarga, membentuk eksistensi diri, dan menumbuhkan rasa kebersamaan antarwarga,” katanya.
Rasa kebersamaan itu, menurut Mimi, adalah inti dari keberlanjutan sosial. “Ketika warga punya rasa memiliki terhadap lingkungannya, mereka akan menjaga, terlibat, dan berpartisipasi. Dari partisipasi itulah keberlanjutan lahir.”
Di banyak kompleks perumahan di Makassar, rasa kebersamaan itu sering teruji. Di perumahan kelas menengah ke bawah, interaksi sosial relatif kuat, tapi sarana umum kerap minim.
Sebaliknya, di kompleks mewah yang tertata rapi, interaksi sosial justru melemah di balik pagar tinggi dan gerbang eksklusif. “Inilah tantangan pembangunan kota modern. Kita terlalu sibuk membangun fisik, tapi melupakan jiwa kotanya,” ujar perempuan kelahiran 18 Desember 1966 ini.
Dalam regulasi, pemerintah telah menetapkan standar yang cukup rinci. Permukiman skala besar, misalnya, wajib menyediakan 30 persen lahan untuk prasarana dan sarana umum (PSU), termasuk ruang terbuka hijau (RTH) dan fasilitas sosial.
Namun di lapangan, hasil penelitian laboratorium menunjukkan bahwa 34 persen perumahan di Makassar tidak memiliki RTH.
“Artinya implementasi masih lemah. Bisa jadi karena aturan belum detail, atau karena pengawasan perizinan belum ketat,” lanjut Guru Besar dalam Bidang Ilmu Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman ini.
Padahal, keberadaan taman-taman kota dan jalur hijau bukan sekadar pemanis visual. Ia adalah paru-paru kota yang bekerja diam-diam, menyerap karbon, menurunkan suhu, dan menjadi ruang resapan air hujan.
Di tengah ancaman banjir yang kerap melanda Makassar, fungsi ekologis ruang hijau menjadi semakin penting. “RTH itu memiliki fungsi ekologi, sosial, ekonomi, hingga edukatif,” kata Mimi.
Di taman, anak-anak belajar mengenal alam, warga berinteraksi, dan pedagang kecil bisa mencari nafkah. “Banyak orang melihat taman sebagai hal sepele, padahal di situlah keseimbangan kota terjaga.”
Standar Rumah Sehat dan Layak Huni
Dalam pandangan Prof. Mimi, rumah yang sehat dan layak huni adalah pondasi utama permukiman berkelanjutan.
Ia menyebut standar minimal yang sering dilupakan: luas bangunan ideal 9 meter persegi per orang, sirkulasi udara dan cahaya masing-masing minimal 5 dan 10 persen dari luas ruangan, serta ketersediaan air bersih yang “tidak berasa, tidak berbau, dan tidak berwarna.”
“Kalau rumahnya sehat, penghuninya juga sehat. Rumah itu bukan cuma tempat berlindung, tapi tempat manusia tumbuh—fisik, mental, dan sosialnya,” ujarnya.
Ia menambahkan, rumah yang baik juga harus “produktif”—dalam arti mendukung aktivitas ekonomi keluarga.
“Banyak ibu rumah tangga sekarang bisa berwirausaha dari rumah, membuat kue, menjahit, atau menjual hasil kerajinan. Kalau rumahnya nyaman, aktivitas itu tumbuh, dan ekonomi keluarga ikut meningkat,” kata Mimi.
Antara Beton dan Hijau: Jalan Tengah Pembangunan
Pertumbuhan Makassar sulit dibendung. Dari reklamasi di pesisir CPI hingga kawasan baru di Talasa dan Untia, proyek-proyek besar terus bermunculan.
Pemerintah provinsi bahkan tengah menyiapkan kawasan reklamasi seluas 1.440 hektar di Untia, dengan 40 persen di antaranya akan difungsikan sebagai permukiman.
Bagi Mimi, pembangunan bukan hal yang harus ditolak, tetapi perlu diarahkan. “Regulasi sudah bagus, tinggal diperketat pengontrolannya,” ujarnya.
“Izin mendirikan perumahan misalnya, harus benar-benar melalui forum kajian perencanaan kota, supaya tata letaknya sesuai dan tidak mengorbankan ruang hijau.”
Ia mengingatkan agar kebijakan tidak sekadar berorientasi pada ekonomi dan investasi. “Investor butuh aturan yang jelas, bukan longgar. Kejelasan itu justru membuat mereka nyaman berinvestasi tanpa merusak lingkungan.”
Dalam peta besar pembangunan kota, akademisi memainkan peran penting sebagai jembatan antara ilmu dan kebijakan.
Di Universitas Hasanuddin, tim dari jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) kerap terlibat sebagai tenaga ahli dalam penyusunan konsep Smart City, penelitian penularan TBC di kawasan padat, hingga perencanaan ruang hijau kota.
Namun, Mimi menekankan bahwa akademisi tidak bisa bekerja sendiri. “Kita butuh kolaborasi lintas sektor—pemerintah, swasta, komunitas, bahkan media,” katanya. “Kalau semua elemen bekerja bersama, hasilnya akan jauh lebih berkelanjutan.”
Ia menyebut konsep penta-helix collaboration sebagai model ideal: sinergi antara akademisi, pemerintah, swasta, komunitas, dan media dalam satu kerangka pembangunan kota.
Mengikis Kumuh, Membangun Harapan
Salah satu tantangan terbesar Makassar hari ini adalah menghapus kawasan kumuh. Program nasional Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) memang berhasil menurunkan tingkat kekumuhan dari kategori berat menjadi ringan, tetapi luasannya justru bertambah. Bagi Mimi, artinya masih banyak warga yang belum benar-benar keluar dari lingkaran ketidakberdayaan.
“Untuk menuntaskan kawasan kumuh, tidak cukup membenahi fisiknya saja,” tegasnya. “Harus juga diberdayakan ekonominya, pendidikannya, dan partisipasi sosialnya.”
Ia mencontohkan, Dinas Pekerjaan Umum bisa memperbaiki infrastruktur rumah dan jalan, sementara Dinas Koperasi atau Tenaga Kerja dapat memberi pelatihan usaha bagi warga. “Dengan begitu, mereka tidak hanya keluar dari kumuh secara fisik, tapi juga mampu mandiri,” ujarnya.
Bagi Makassar, jalan menuju permukiman berkelanjutan masih panjang. Tetapi, di balik gedung-gedung yang menjulang dan jalan yang kian sesak, selalu ada ruang untuk harapan.
Di banyak sudut, komunitas warga mulai menanam pohon di halaman rumah, membuat taman kecil di gang sempit, atau mengelola bank sampah bersama.
Mimi tersenyum ketika mengingatkan satu hal sederhana. “Permukiman berkelanjutan itu dimulai dari kesadaran kecil. Yaitu rasa memiliki terhadap tempat tinggal kita,” ujarnya. (*)